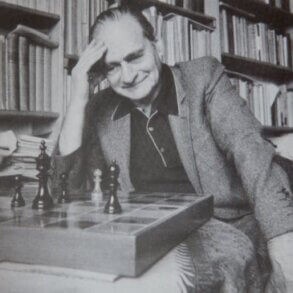Berpimpinan, berpelukan dan berbahagia dengan pasangan yang kita cintai adalah hal yang menyenangkan. Bahagia dan membahagiakan. Cinta dan mencintai. Sayang dan menyayangi. Rindu dan merindui. Perkahwinan adalah pilihan. Sedang cinta tidak boleh dipaksakan. Hidup ini bukan tentang Full House. Atau Vanilla Coklat. Ia lebih gelap dan kadangkala memeritkan. Kalau ada perempuan yang memilih untuk berkahwin, bererti ada perempuan yang memilih untuk tidak menjadi isteri. Perkahwinan adalah pilihan. Dan dikahwini juga adalah pilihan. Kalau perkahwinan dipaksakan tanpa kerelaan perempuan – ia satu kezaliman.
Kartini dikurung dalam ruang adat yang tidak berpintu. Tidak berpintu, tidak berjendela, tidak satu pun membenarkan Kartini keluar berlari dan bebas. Dalam adat yang menentukan nasib perempuan itu, orang perempuan harus kekal di rumah sehingga akhirnya dipilih orang. Kalau nanti orang perempuan dipinang lelaki, barulah mereka keluar dan sebuah pintu tiba-tiba muncul di tengah ruang yang tadinya cuma dinding batu tak terpecahkan.
“Pada usia 12 tahun, saya harus tinggal di rumah. Saya harus tinggal di “kotak”, terkurung di rumah, terasing dari dunia luar. Saya tidak boleh kembali ke dunia itu selama belum memiliki suami – seorang lelaki yang sama sekali asing, yang dipilih orang tua kami untuk menikahi kami, sungguh tanpa sepengetahuan kami.”
Perkahwinan adalah tentang kehidupan dan masa hadapan. Lalu, tidak boleh tidak perempuan mesti punya suara dalam menentukan pasangan hidup sendiri. Ia bukan tentang berganti milik melainkan meneruskan hidup dan merempuh badai.
Mempunyai autoriti, kehendak dan berhak terhadap keputusan dan hidup sendiri merupakan satu hal yang sering sahaja menjadi krisis dalam hidup seorang perempuan. Kita menyaksikan pertengkaran demi pertengkaran kalau perempuan mesti akur akan pilihan orang tua dalam menentukan jodoh dan pasangan. Disokong lagi dengan dalil-dalil misoginis yang langsung tidak manusiawi. Adakah kita mengabaikan sama sekali pendapat bahawa tidak sah perkahwinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka. Adakah kita sama sekali mengabaikan pendapat kalau perkahwinan dengan ikrah adalah sebuah perkahwinan dengan akad yang fasad. Adakah kita sekali lagi mengabaikan peristiwa Khansa binti Khidam al-Ansyariyah yang dikahwinkan bapanya tanpa rela? Atau kita sebenarnya mengabaikan suara perempuan?
Itu menurut Kartini – kalau perkahwinan mesti dipersetujui perempuan. Tak seorang pun dan tak sesiapa pun berhak menjual kehidupan perempuan kepada seseorang yang tidak dikenali.
“Di dunia kami, pernikahan dapat terjadi di luar pengetahuan si gadis sama sekali. Untuk melangsungkan pernikahan, hanya diperlukan izin ayah, paman atau kakak (abang) si gadis. Pada akad nikahnya si gadis sama sekali tidak perlu hadir. Kecuali apabila ia tidak mempunyai ayah, paman atau kakak, ia harus hadir pada pernikahannya. Wali kami dapat mengahwinkan kami dengan orang yang dikehendaki. Hanya dalam satu hal orang tua kami tidak boleh memaksa kami, apabila calon mempelai itu dari golongan yang lebih rendah dari kami. Orang tua tidak boleh memaksa anak perempuannya menikah dengan golongan yang lebih rendah darinya. Itu senjata tunggal untuk kami melawan kesewenang-wenang wali kami.
Untuk menikah, orang laki-laki hanya diharuskan pergi ke penghulu atau orang lain bersama ayah, paman atau kakak si gadis. Pernikahan tetap dilangsungkan, walaupun anak perempuan itu tidak mahu menerimanya. Dia akan dinikahkan jika orang tuanya menghendaki.”
Namun, dengan keterbatasan, Kartini tetap akur dengan adat perkahwinan paksa-rela. Kalau ada perkahwinan yang gagal dan menyeksakan, cuma air mata mengiringi simpati. Cuma gelora di dada berhempas bersama empati. Begitulah sakit jiwanya melihat pernikahan Kardinah yang gagal, hancur dan berantakan. Daya apakah yang dia punya untuk menentang orang tua?
Kedua, perkahwinan ialah panggilan hidup. Ia hadir ketika kita mahukan. Dan bukan satu rukun yang dilakukan demi meneruskan kehidupan. Hari ini, kita berhadapan dengan gelombang perkahwinan yang maha dahsyat. Kanak-kanak dikahwinkan. Orang-orang miskin memilih mengahwinkan anak perempuan demi kelangsungan hidup. Ia menyedihkan. Perempuan sering diajarkan kalau mereka tidak perlu bermatian mengejar dunia. Tidak perlulah orang perempuan bersungguh-sungguh melengkapkan diri dengan pendidikan kelak ada suami yang bakal menjadi sumber penghidupan. Kelak, tatkala perempuan ditinggal suami (berpisah atau dengan kematian), melaralah orang perempuan menjadi ibu tunggal tak berpendidikan. Mereka bukan patah sebelah sayap melainkan rebahlah kedua-keduanya. Apatah lagi, kanak-kanak. Apatah lagi, mereka yang dijual masa hadapannya kerana kemiskinan yang menjerut. Sudah sakit menjadi perempuan. Sakit lagi menjadi perempuan yang tenggelam dalam bah kemiskinan.
“Pernikahan seharusnya menjadi panggilan hidup, kini berubah menjadi sumber penghidupan. Dan aduhai! Banyak perempuan Jawa harus menikah dengan perjanjian yang menghinakan dan merendahkan dirinya sendiri. Di bawah perintah ayah, paman atau kakaknya, anak perempuan harus bersedia mengikuti laki-laki yang sama sekali asing baginya, bahkan punya anak dan isteri.”
Ketiga, menurut Kartini, dalam sebuah ikatan perkahwinan, poligami adalah hal yang melukakan hati perempuan. Ia lebih parah apabila ia sudah menjadi adat kebiasaan bangsawan Jawa. Apalah ertinya menjadi isteri yang merampas kebahagiaan perempuan lain. Kartini meskipun memahami hukum agama yang membenarkannya, tetap, baginya adat ini memangsakan perempuan. Hari ini, di Malaysia, bukanlah agama yang ditentang melainkan pentafsirannya yang sering sahaja menyebelahi lelaki. Undang-undang ciptaan manusia yang sering sahaja menafikan hak perempuan ini tidak boleh tidak mesti dikaji semula seterusnya memberikan keadilan kepada perempuan dalam persoalan poligami.
Namun, orang perempuan, apa yang mahu kita takutkan? Bebaskan diri. Kelak poligami bukan lagi ancaman. Membincangkan poligami adalah hal yang boleh dikatakan tabu. Tidaklah dapat dibincangkan tanpa tuduhan menolak hukum Tuhan, ia merupakan ancaman liberalisme dan persoalan akidah yang mesti dilafazkan semula syahadah. Apa sahajalah hal perempuan yang boleh dibincangkan?
“Semua perbuatan, yang menyebabkan semua manusia menderita, saya anggap sebagai dosa. Dosa adalah menyakiti makhluk lain, manusia atau binatang. Dan apakah kamu membayangkan siksaan yang harus diderita seorang wanita, jika suaminya pulang bersama wanita lain sebagai saingannya yang harus diakui sebagai isteri yang sah? Suami dapat menyiksanya sampai mati, menyakiti semahunya. Kalau suaminya tidak mahu menceraikannya, sampai mati pun wanita itu tidak akan memperoleh hak! Semua untuk laki-laki dan satu pun untuk wanita. Itulah hukum dan ajaran kami.”
Dalam melayari bahtera perkahwinan, seorang perempuan mesti diajarkan ilmu rumahtangga. Dalam adat Jawa yang mengurung perempuan ketika itu, orang perempuan tidak dibenarkan keluar rumah apatah lagi ke sekolah. Orang perempuan dibiarkan dihempap batu kebodohan sehingga tidaklah diberikan pendidikan. Sedangkan, orang perempuanlah yang bakal menjadi guru pertama anak-anak di rumah menurutnya. Kartini percaya kalau perempuan, mesti terdidik dengan baik sedari awal agar generasi kemudiannya mendapat manfaat daripadanya.
Kini, orang perempuan ramai terdidik. Dibenar keluar dan diizin belajar. Satu didikan yang mesti diketahui ialah hak yang sebenar sebagai seorang isteri. Bukan sahaja keperluan, termasuklah haknya ke atas tubuh sendiri. Ilmu rumahtangga menurut Kartini adalah mudah dan seharusnya tidak dilabel sebagai ilmu rumahtangga melainkan ilmu asas kehidupan. Ia termasuklah memasak, cekap melakukan kerja tangan, cekap mengurus kewangan dan mahir ilmu baca tulis. Hari ini, isteri perlu tahu lebih dari itu. Seorang perempuan mesti dilengkapkan dengan pengetahuan undang-undang perkahwinan sebaiknya. Selengkapnya. Termasuklah hak-hak selepas penceraian, hak di ranjang, hak kepada harta, hak sebagai isteri yang dimadukan sehingga tiada ruang untuk ketidakadilan.
Akhir sekali, bukan sahaja menurut Kartini malah menjadi harapan kita semua, dalam sebuah perkahwinan mesti dihadirkan seorang suami yang setia menjadi pendukung. Ketika Kartini bersikap kritis terhadap perkahwinan, tidaklah Kartini sepenuhnya menafikan perkahwinan yang disirami kebahagiaan. Pernikahannya membahagiakan kerana ia sesuai dengan harapan. Cita-citanya yang membuak-buak disahut dan digenggam oleh sang suami.
“Calon suami saya akan mendampingi saya sekuat tenaganya untuk bekerja demi keselamatan bangsa kami. Kami berdua akan saling membantu dan mengisi. Dan bagaimana saya sekarang merencanakan akan melaksanakan cita-cita saya? Saya belajar terus, juga kalau saya sudah kahwin.”
Begitulah perkahwinan tidak seharusnya merencatkan kehidupan. Tidak boleh menjadi penghalang cita-cita. Lelaki juga punya peranan penting dalam dunia serba menindas perempuan. Ketika perempuan mahu keluar dari penjara patriarki ini, orang laki-laki tidak seharusnya menutup kembali jalan yang sedikit demi sedikit dibuka dan diteroka oleh perempuan.
Sikap Kartini yang kritis tentang pernikahan ini mencampakkan mawar kepada dirinya. Wangi dan menyenangkan. Perkahwinan ialah sebuah belantara yang mesti diteroka sendiri. Justeru, pilihannya ada di tangan masing-masing kerana yang melaluinya ialah diri kita sendiri. Ingatlah, perkahwinan ialah pilihan, bukan rukun kehidupan.