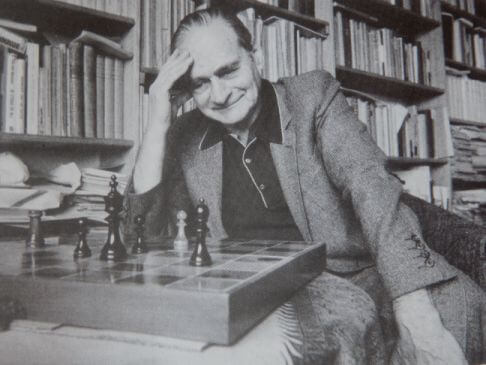Sebagai intelektual pada masanya, Wertheim membaca ulang kembali korupsi dalam tulisannya sebagai fenomena sosiologis, alih-alih sekadar masalah moral, hukum, atau ekonomi. Tulisan ini diterbitkan pada masa ketika banyak kajian tentang korupsi didominasi oleh sarjana ilmu administrasi publik. Ia menawarkan penjelasan historis, komparatif, dan struktural. Analisisnya menempatkan pengalaman korupsi di Asia Tenggara dalam lintasan kolonialisme, patrimonialisme, dan kemunculan birokrasi.
Salah satu bagian menarik di awal esai Wertheim terletak pada pembahasannya tentang VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) dan warisannya di Hindia Belanda. Lebih dari sekadar perusahaan dagang, VOC mengembangkan ciri-ciri yang menyerupai negara, lengkap dengan birokrasi, sistem perpajakan, dan praktik patrimonial. Ia menyoroti bagaimana VOC mewujudkan struktur birokrasi-patrimonial, mengaburkan batas antara otoritas publik dan keuntungan pribadi.
Wertheim mengutip surat-surat Dirk van Hogendorp, seorang kritikus korupsi kolonial yang vokal, yang menggambarkan bagaimana para administrator di Batavia secara rutin menyalahgunakan wewenang melalui pungutan jabatan, penyelundupan serta penyuapan. Hogendorp sendiri mengecam bagaimana para pejabat harus membayar selangit untuk mengamankan posisi, yang kemudian menutupi biaya tersebut dengan memeras penduduk setempat. Wertheim menafsirkan hal ini sebagai bukti bahwa korupsi ialah bagian struktural dari pemerintahan kolonial. Baginya, Hogendorp secara tidak langsung menginternalisasi nilai-nilai Eropa yang sedang berkembang, yaitu akuntabilitas dan efisiensi. Dalam kritiknya, Wertheim melihat benih-benih awal kesadaran sosiologis yang kemudian berkembang menjadi norma-norma antikorupsi modern.
Wertheim tidak membatasi analisisnya hanya pada Asia Tenggara. Ia menempatkan pengalaman kolonial Belanda dengan Prancis di era Napoleon, dengan mengambil inspirasi dari para sejarawan seperti Presser. Menurutnya, reformasi administrasi tahun 1800an dianggap sebagai momentum revolusioner, meminjam istilah Weber yakni “negara birokrasi modern”, sebuah sistem di mana jabatan-jabatan digaji, diatur secara hierarkis, terikat aturan, dan semakin terisolasi dari praktik-praktik patrimonial. Meskipun reformasi birokrasi menciptakan ekspektasi baru akan efisiensi dan akuntabilitas, Wertheim mencatat bahwa sistem Napoleon pun penuh dengan celah hukum, favoritisme, dan pengawasan yang lemah. Alhasil, pengawasan terhadap pejabat menjadi tidak efektif, sehingga muncul godaan mencari keuntungan yang terus-menerus dalam sistem birokrasi.
Korupsi di Asia Tenggara tidak dapat dipahami tanpa merujuk pada kondisi global karena faktor tumbuhnya patrimonialisme yang tidak hanya terjadi di Asia tetapi juga cerminan pemerintahan Eropa hingga abad ke-18 hingga ke-19. Yang dimaksud dengan patrimonialisme di sini adalah bentuk pemerintahan di mana penguasa memerintah berdasarkan loyalitas pribadi yang berasal dari hubungan patron-klien, kesetiaan pribadi, ikatan kekerabatan, dan kombinasinya.
Patrimonialisme di Jawa dan Sekitarnya
Dalam studinya mengenai Asia Tenggara, Wertheim memberikan analisis rinci tentang Jawa di bawah pemerintahan kolonial dan pribumi. Kegagalan Jenderal Daendels untuk menerapkan reformasi administrasi di Jawa menunjukkan kuatnya praktik patrimonial. Para bangsawan dan bupati Jawa menolak integrasi ke dalam birokrasi bergaya Barat, karena takut kehilangan hak istimewa yang sudah menjadi tradisi secara turun-temurun. Alhasil, sistem hibrida diterapkan, di mana birokrat Eropa hidup berdampingan dengan penguasa lokal yang terus memungut upeti dan tenaga kerja menyesuaikan tradisi dan adat setempat.
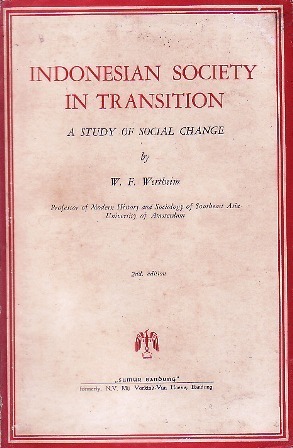
Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel) yang diperkenalkan pada abad ke-19 semakin melembagakan korupsi hibrida ini. Para bangsawan diizinkan untuk mengklaim persentase tertentu dari hasil tanam paksa, sementara pejabat Eropa sering memperkaya diri sendiri melalui pungutan liar dan pembayaran sampingan. Bagi Wertheim, pengaturan ini mengaburkan batas antara perpajakan yang sah dan pemerasan, yang juga menunjukkan bagaimana korupsi seringkali bergantung pada pandangan orang yang melihatnya.
Pola serupa juga terjadi di koloni-koloni lain. Di perkebunan tembakau Sumatra, sebagaimana dijelaskan oleh Van den Brand dalam The Millions from Deli, korupsi terwujud melalui suap tidak langsung, harga lelang yang melambung, dan kolusi sistematis antara pemilik perkebunan dan pejabat kolonial. Dalam hal ini, Wertheim melihat bagaimana mekanisme tersebut jarang terlihat, melainkan tertanam dalam transaksi sehari-hari, mencerminkan apa yang disebut H.J. Brasz sebagai “kerahasiaan dan pengakuan bersama” yang mendefinisikan korupsi.
Wawasan Sosiologis: Relativitas Korupsi
Wertheim berpendapat bahwa tindakan yang dianggap korup dalam norma-norma modern seringkali diterima secara sosial dalam konteks sebelumnya. Pembayaran upeti, pemberian hadiah, dan pertukaran patron-klien merupakan praktik adat yang menjamin loyalitas dan stabilitas. Baru dengan munculnya rasionalisme birokrasi dan ekonomi kapitalis, praktik-praktik ini menjadi terdelegitimasi. Elit Tionghoa di Jawa dan Sumatra diberikan peran seperti mengendalikan pegadaian, perjudian, dan perdagangan opium, mereka beroperasi dalam sistem yang ditoleransi oleh otoritas kolonial. Namun, bagi penduduk lokal, kegiatan-kegiatan ini seringkali bersifat represif.
Wertheim juga menggarisbawahi sifat korupsi yang melibatkan tiga pihak: pemberi, penerima, dan masyarakat sekitar yang menilai tindakan tersebut. Pembingkaian sosiologis ini menggerakkan diskusi melampaui biner sederhana legal/ilegal atau moral/amoral, menuju pemahaman bernuansa tentang korupsi sebagai praktik sosial yang diperebutkan.
Selanjutnya, Wertheim menyoroti bagaimana nepotisme dan favoritisme berakar kuat dalam norma-norma sosial Jawa, di mana kesetiaan kepada keluarga dan kerabat seringkali lebih penting daripada kesetiaan kepada institusi. Praktik-praktik seperti memberikan hadiah kecil (buah-buahan, ayam, keranjang hadiah) kepada pejabat mengaburkan batas antara ekspresi budaya penghormatan dan gagasan suap yang lebih modern. Pemerintah kolonial, meskipun secara nominal berkomitmen pada rasionalitas birokrasi, seringkali menoleransi atau bahkan mendorong praktik-praktik semacam itu untuk mengamankan kerja sama para bangsawan lokal dan elit administrasi.
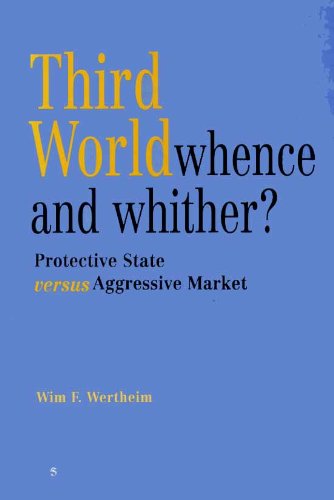
Bahkan, Wertheim menekankan bahwa penguasa kolonial seringkali menutup mata terhadap penyimpangan dalam pengelolaan keuangan demi menjaga kesetiaan para bangsawan pribumi yang berperan sebagai pilar administrasi. Hal ini menghasilkan apa yang ia sebut “hubungan patrimonial” yang mengikat negara kolonial dengan struktur kekuasaan lokal, memastikan stabilitas tetapi melanggengkan korupsi dengan kedok kewajiban adat.
Upaya Reformasi
Dalam esai Wertheim juga membahas upaya reformasi di bawah tokoh-tokoh seperti Gubernur Jenderal Dirk Fock, yang melancarkan pembersihan antikorupsi di awal abad ke-20, yang menyasar pejabat yang menjalankan komisi rahasia atau menggelapkan dana publik. Namun, upaya ini dirusak oleh jaringan yang mengakar dan standar ganda pemerintahan kolonial. Sementara pejabat Eropa diharapkan mewujudkan cita-cita birokrasi, pejabat Indonesia seringkali dinilai dengan standar yang lebih lunak, yang memperkuat persepsi korupsi sebagai sistemik dan dapat ditoleransi.
Namun, Wertheim mengingatkan para pembaca bahwa korupsi bukan sekadar “patologi Timur.” Ia mendokumentasikan bagaimana pejabat Belanda sendiri terlibat dalam skema-skema mencari keuntungan, seringkali melalui koneksi dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Royal Dutch Petroleum Company. Batas yang kabur antara layanan publik dan perusahaan swasta, baik melalui suap langsung maupun pergantian pejabat ke dewan direksi perusahaan, mengilustrasikan dimensi global, bukan regional, dari korupsi.
Indonesia Pasca-Kemerdekaan: Tekanan Struktural dan Korupsi Baru
Dengan kemerdekaan, faktor-faktor struktural baru membentuk kembali lanskap korupsi. Wertheim mengidentifikasi dua perkembangan penting. Pertama, perluasan fungsi birokrasi. Pasca merdeka, Indonesia dengan cepat memperluas tanggung jawabnya, terutama dalam mengatur dan mengendalikan perekonomian. Hal ini menyebabkan lonjakan jumlah pegawai negeri sipil, yang banyak di antaranya tidak memiliki pelatihan memadai atau etos birokrasi. Kesenjangan antara meningkatnya tanggung jawab dan terbatasnya kapasitas administratif menciptakan lahan subur bagi korupsi.
Kedua, gaji rendah dan tekanan gaya hidup. Wertheim menyoroti masalah kronis rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Banyak pejabat terpaksa mencari penghasilan tambahan melalui pembayaran sampingan, pemerasan, atau penyalahgunaan wewenang. Ia mencatat bahwa hal ini diperparah oleh “peragaan gaya hidup” yakni tuntutan gaya hidup yang mencolok yang dibebankan kepada para elit, yang diharapkan untuk mempertahankan standar kemewahan di tengah kelangkaan. Kesenjangan antara pendapatan resmi dan ekspektasi sosial ini mengukuhkan korupsi sebagai strategi bertahan hidup sekaligus pengejaran kekayaan. Dinamika ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Wertheim menempatkannya dalam pola Asia Tenggara yang lebih luas, di mana ekspansi negara pascaperang tidak diimbangi oleh perlindungan kelembagaan yang diperlukan untuk mencegah korupsi.
Faktor kunci pasca-kemerdekaan lain yang diidentifikasi Wertheim adalah meningkatnya peran penegak hukum termasuk di dalamnya militer dalam politik dan administrasi. Di Indonesia, Myanmar (Burma), dan Filipina, para penegak hukumnya sering kali membenarkan intervensi mereka dalam menangani persoalan ini. Namun, Wertheim menunjukkan ironi bahwa pemerintahan tersebut seringkali memperparah korupsi, alih-alih menyelesaikannya. Para elit lokal di Indonesia, misalnya, terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal seperti penyelundupan hasil bumi seperti kopra di Sulawesi untuk mengamankan devisa. Alih-alih memberantas korupsi, keterlibatan penegak hukum ini justru mendiversifikasi bentuk dan penerima manfaatnya.
Pada akhir 1950-an, Wertheim menyimpulkan bahwa korupsi pascakolonial di Indonesia tetap dibentuk secara mendalam oleh struktur sosial tradisional. Praktik-praktik seperti upeti, loyalitas kekerabatan, dan pertukaran patrimonial tetap ada, kini berlapis-lapis pada lembaga-lembaga politik dan birokrasi modern. Hibriditas ini menjelaskan mengapa langkah-langkah antikorupsi, baik itu pembersihan kolonial, kampanye nasionalis, maupun pengambilalihan oleh penegak hukum termasuk militer, berjuang untuk menghasilkan perubahan yang langgeng. Pada saat yang sama, Wertheim mengakui adanya pergeseran budaya yang sedang terjadi. Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa menyelaraskan gaji, ekspektasi gaya hidup, dan etos birokrasi, korupsi akan tetap endemik.
Kesimpulan
Tulisan Segi-segi Sosiologi Korupsi di Asia Tenggara karya Wertheim ini menggarisbawahi tesis utamanya yakni korupsi bukanlah anomali, melainkan cerminan struktur sosial, tatanan kelembagaan, dan norma budaya. Dari patrimonialisme di bawah pemerintahan kolonial hingga ekspansi birokrasi pasca-kemerdekaan, dari retorika nasionalis hingga intervensi penegak hukum termasuk militer, korupsi terus berlanjut di Asia Tenggara karena reformasi gagal mengatasi logika sosial yang mendasarinya.
Dengan merangkai kasus-kasus historis, analisis komparatif, dan wawasan sosiologis, Wertheim mendorong pembaca untuk melihat korupsi bukan hanya sebagai penyimpangan, tetapi sebagai elemen konstitutif dari masyarakat transisi. Ia juga menunjukkan bagaimana korupsi beradaptasi dengan realitas politik baru sambil mempertahankan fondasi budaya lama. Pesan Wertheim tetap relevan yakni strategi antikorupsi yang efektif harus bergulat tidak hanya dengan kerangka hukum tetapi juga dengan gaji, tekanan gaya hidup, dan keterikatan pejabat negara dalam jaringan sosial yang lebih luas. Analisis dan reformasi yang efektif memerlukan perhatian pada warisan sejarah, praktik budaya, dan interaksi kompleks antara patrimonialisme dan rasionalisasi birokrasi.
Penulisan ini merujuk Esei E. F. Wertheim bertajuk ‘Segi Segi Sosiologi Korupsi di Asia Tenggara’ dalam buku Etika Pegawai Negeri (1977) yang disunting oleh Mochtar Lubis dan James C Scott.