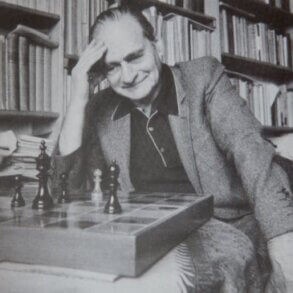Pada tahun 2023, Syaza Shukri menerbitkan sebuah artikel dalam jurnal Religions yang menggambarkan Malaysia sebagai satu kes Islamist civilizationism. Dengan merujuk kepada literatur populisme peradaban, beliau berhujah bahawa politik Melayu-Muslim mewakili sebuah projek Islamis bagi mempertahankan peradaban, dan meletakkan Mahathir Mohamad sebagai tokoh utama dalam trajektori tersebut. Hujah beliau turut menempatkan UMNO, PAS dan ABIM sebagai sebahagian daripada kebangkitan Islam yang lebih besar, yang menggunakan idiom “peradaban” untuk mengukuhkan identiti Melayu-Muslim.
Pada pandangan pertama, hujah ini kelihatan meyakinkan. Malaysia sememangnya menyaksikan agama digunakan dalam bentuk populis — dalam Gelombang Hijau, dalam retorik PAS mempertahankan Islam, dan dalam kegelisahan Melayu-Muslim yang dibingkaikan sebagai ancaman daripada “yang lain.” Namun menggambarkan Malaysia hanya sebagai “populisme peradaban Islamis” adalah rumit dan mengelirukan. Masalahnya bukan kerana wujudnya retorik peradaban, tetapi kerana kesilapan mengenal pasti pemacunya. Mahathir bukanlah seorang Islamis. Dan yang lebih penting: Islamisme tidak pernah hanya bersifat politik. Ia sentiasa bersifat peradaban.
Populisme bergantung pada proses othering. Ia mencipta sempadan antara “rakyat”, yang dibayangkan sebagai suci dan sah, dan “yang lain”, yang ditampilkan sebagai korup, mengancam, atau asing. Di Malaysia, hal ini telah lama beroperasi melalui binari Melayu-Muslim versus Cina/liberal/seksular.
Namun Islamisme melangkah lebih jauh. Keseluruhan epistemologinya dibina di atas othering. Projek Islamisasi Ilmu (IoK) yang dirumuskan oleh Syed Naquib al-Attas memaku binari tersebut pada aras intelektual: ilmu Islam sebagai kebenaran, ilmu Barat/liberal/sekular sebagai kesesatan. Peng-other-an ini kemudiannya mengalir ke dalam manifestasi politik dan sosial: ketuanan Melayu-Islam ala ISMA (Melayu-Muslim sebagai teras sah, bukan Muslim sebagai pinggiran yang ditoleransi); perubahan PAS daripada “PAS for All” kepada supremasi majoritarian; Islam Kosmopolitan ABIM yang tetap meletakkan Islam sebagai pusat; serta Negara Rahmah IKRAM yang membalut hierarki dalam bahasa belas kasihan.
Di sebalik semua variasi ini, logiknya tetap konsisten: Islam ialah pusat peradaban, manakala selebihnya ialah penyimpangan. Populisme menyediakan persembahan, tetapi Islamisme menyediakan epistemologi. Di sinilah perbezaan kritikal itu terletak: populisme bersifat bising dan tidak konsisten, bergantung kepada himpunan massa dan kitaran pilihan raya; Islamisme pula bersifat struktural dan konsisten, membentuk undang-undang, birokrasi dan produksi pengetahuan. Sebab itu Islamisme tidak boleh dipisahkan daripada peradaban — ia memang direka sebagai projek peradaban. Politik, dakwah dan pendidikan bukan domain yang terpisah, tetapi manifestasi daripada horizon yang sama.
Mahathir, Anwar dan Al-Attas: Trifekta Islamisasi Malaysia
Di sinilah letaknya kesilapan paling ketara dalam artikel Shukri. Dengan meletakkan Mahathir sebagai “ketua” kepada populisme peradaban Islamis, beliau telah mencampurkan beberapa logik yang berbeza menjadi satu. Islamisasi Mahathir bukanlah Islamis. Ia merupakan Islam neoliberalisme: teknokratik, memodenkan, dan berorientasikan pembangunan. Islam dimobilisasikan sebagai alat legitimasi negara, satu cara untuk mengukuhkan nasionalisme Melayu dan menampilkan Malaysia sebagai sebuah negara Islam moden.
Namun UMNO di bawah Mahathir bukanlah sekadar “UMNO Mahathir.” Sejak 1982, parti itu telah dimasuki oleh figura-figura ABIM, bermula dengan Anwar Ibrahim. Mahathir menyediakan wahana pembangunan; Anwar pula membekalkan tatabahasa ideologi. Anwar dan kader-kader ABIM-lah yang mengoperasikan tadbir urus Islam dalam kerangka neoliberalisme UMNO, menjadikan perbankan Islam, universiti Islam dan birokrasi Islam sebagai lambang civilisational Islam. Tanpa tenaga ideologi ABIM, UMNO tidak mungkin menampilkan Islamisasi sebagai bentuk tadbir urus, bukan hanya dasar.
Dalam pengertian ini, Mahathir membina mesinnya, tetapi Anwar menggerakkannya dengan ideologi. Perkahwinan antara neoliberalisme UMNO dengan tatabahasa peradaban ABIM mencipta bentuk hibrid Islamisasi yang terus mendefinisikan trajektori Malaysia sampai hari ini.
Adalah suatu kesilapan untuk mereduksi Islamisasi di Malaysia kepada pragmatisme negara Mahathir atau perjalanan ideologi peribadi Anwar Ibrahim. Asas yang lebih dalam terletak pada projek Islamisasi Ilmu (IoK), sebagaimana dihuraikan oleh Syed Naquib al-Attas dan diinstitusikan di Malaysia melalui universiti, kurikulum dan wacana birokratik. Seperti yang ditunjukkan oleh Mona Abaza, IoK bukanlah eksperimen intelektual pinggiran tetapi menjadi perancah ideologi kepada keseluruhan projek Islamisasi negara.
IoK mentakrifkan semula ilmu dengan menetapkan sebuah binari: ilmu Islam sebagai kebenaran ilahi, ilmu Barat/liberal/sekular sebagai penyimpangan yang tercemar. Penutupan epistemik ini menyediakan justifikasi untuk projek Islamisasi yang diterajui negara. Universiti Islam, ekonomi Islam, kewangan Islam, dan latihan birokrasi dibingkaikan sebagai lanjutan visi ini. IoK bukan sekadar mengiringi Islamisasi, ia membentuk strukturnya.
Apabila Anwar dan kader ABIM memasuki UMNO, mereka menggunakan kerangka Attasian ini untuk memberikan inti ideologi kepada projek-projek birokratik. Birokratisasi Mahathir boleh mengemukakan bank Islam atau universiti Islam sebagai simbol kemodenan; tetapi IoK menyediakan bahasa epistemologi untuk mempersembahkannya sebagai blok binaan sebuah peradaban Islam. Dengan cara ini, logik negara pembangunan bercantum dengan logik Islamisme yang menuntut ketuanan epistemik.
Tadbir Urus Sakral dan Islamisme Mencair: Kehidupan Sosial Sebuah Projek Peradaban
Islamisasi Mahathir mengukuhkan kedudukan Islam melalui pembirokrasian: perbankan dan kewangan Islam, universiti dan sekolah Islam, ekonomi Islam, serta penubuhan BAHEIS dan kemudian JAKIM untuk menyelaras hal ehwal agama. Pada permukaannya, ini kelihatan seperti proses pembinaan negara — memodenkan Islam, memprofesionalkan pentadbirannya, dan menyeragamkan governansnya. Namun logik pembirokrasian, pemprofesionalan dan penyeragaman inilah sebenarnya bentuk Islam yang dibayangkan oleh Islamis.
Jauh daripada kerencaman, kepelbagaian dan kelenturan tradisi Islam yang sebenar, Islamis berusaha mencipta semula Islam dalam bentuk moden: seragam, berpusat dan distandardkan. Seperti yang dihujahkan Bassam Tibi, Islamisme bukanlah kesinambungan tradisi, tetapi satu penciptaan semula tradisi. Visi Islamis tentang peradaban bukanlah tentang memelihara kepelbagaian, tetapi membina satu tatanan tunggal, di mana Islam boleh disistematisasikan ke dalam institusi, birokrasi dan kod tingkah laku dan moral.
Inilah sebabnya projek Islamisasi berkembang dalam dua arah serentak. Dari atas, negara memperluas birokrasinya, mengakar Islam ke dalam struktur governans. Dari bawah, Islamis bekerja melalui dakwah, pendidikan dan gerakan sosial untuk menanam kesedaran agama yang konservatif, menghasilkan “persekitaran Islamik” yang menormalkan imaginasi Islamisme. Kedua-dua arus ini menghasilkan sebuah projek peradaban: penciptaan semula Islam sebagai sebuah tatanan moden yang diseragamkan, dibenarkan sebagai kebenaran Ilahi tetapi beroperasi melalui kuasa birokratik.
Walaupun tadbir urus disakralkan menggambarkan bagaimana negara mewujudkan autoriti ketuhanan, projek peradaban Islamisme tidak terhenti pada struktur institusi. Kekuatan utamanya terletak pada keupayaannya memanjangkan logik moral pentadbiran Ilahi ke dalam ruang sosial.
Jika Islamisme bersifat peradaban pada horizonnya, pengukuhannya tidak terbatas kepada negara atau institusi politik. Ia meresap ke dalam kehidupan seharian — di mana kesalehan, konsumsi dan gaya hidup menjadi medan perjuangan ideologi. Projek tadbir urus disakralkan Islamis dikukuhkan bukan sahaja oleh kuasa negara tetapi juga melalui penghasilan sosial religiositi. Kesedaran agama yang dipromosikan Islamis telah lama melampaui lingkungan Islamis formal dan kini memenuhi moral awam serta aspirasi sosial.
Seperti diperhatikan Hew (2017) dalam kajiannya di Malaysia dan Indonesia, liquid Islamism menangkap proses difusi ini: bagaimana Muslim kelas menengah yang saleh menterjemahkan religiositi ke dalam amalan budaya urban — kafe Islamik, butik fesyen, komuniti berpagar, dan ruang patuh syariah — menjadikan konsumsi biasa satu persembahan moral dan ekspresi politik. Ruang-ruang ini mewujudkan imaginasi peradaban Islamisme tanpa perlu memakai label politiknya secara terang-terangant.
Mengembangkan daripada formulasi Hew, saya menggunakan istilah Islamisme cair untuk menggambarkan bagaimana projek peradaban ini meresap ke dalam kehidupan seharian melalui konsumsi bermoral dan aspirasi sosial. Tidak seperti kempen ideologi terang-terangan gerakan Islamis, Islamisme cair beroperasi melalui resapan ke dalam norma kebiasaan dan kebiasaan — dengan menjadikan keagamaan kelihatan seperti gaya hidup, moraliti seperti penjenamaan, dan tatanan Ilahi sebagai tekstur kehidupan normal.
Islamis tidak semestinya berhasrat menjadikan semua anggota masyarakat sebahagian daripada gerakan mereka. Sebaliknya, mereka mahu memastikan bahawa doktrin, simbol dan sensiviti moral mereka diterima, dinormalkan dan diinstitusikan dalam kehidupan seharian. Penyerapan dan internalisasi ini berlaku melalui sistem pendidikan, universiti, institusi kesihatan dan badan birokrasi, di mana aktor Islamis membentuk persekitaran moral melalui reka bentuk kurikulum, budaya institusi dan advokasi dasar. Normalisasi hijab, misalnya, tidak dicapai hanya melalui pujukan individu tetapi melalui penginstitusian dan jangkaan sosial. Begitu juga, kempen menetapkan kod pakaian “sopan” bagi penjawat awam menunjukkan bagaimana moraliti agama menjadi sebahagian daripada aturan birokratik. Dengan cara ini, Islamisme cair menjadikan ruang sosial lanjutan hidup bagi tadbir urus yang disakralkan, secara lembut menerapkan autoriti Ilahi ke dalam operasi harian masyarakat. Proses penyerapan yang berlaku sehari-harian inilah yang membentuk infrastruktur berkesan projek peradaban Islamisme: melalui reproduksi sosial, autoriti Ilahi memperoleh posisinya, dan melalui pembentukan moral, kuasa dipertahankan melampaui sebatas politik sehari-hari.
Perkembangan Islamisasi di Malaysia tidak boleh dipisahkan daripada penginstitusian undang-undang Syariah. Apa yang bermula sebagai pembirokrasian — bank Islam, universiti Islam, JAKIM, BAHEIS — berkembang menjadi sebuah apparatus perundangan yang meluas, menggunakan kedudukan perlembagaan Islam sebagai asasnya. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan, yang menyatakan Islam sebagai agama Persekutuan, menjadi klausa yang “diweaponise” untuk mengabsahkan autoriti birokrasi agama.
Pada 1980-an dan 1990-an, pindaan perlembagaan (terutama Perkara 121(1A) pada 1988) serta enakmen negeri meletakkan asas tersebut. Mahkamah Syariah diperkasakan, fatwa memperoleh kuasa undang-undang apabila digazetkan, dan jabatan agama negeri diberikan kuasa penguatkuasaan yang lebih luas ke atas undang-undang keluarga dan kesalahan moral.
Namun pada 2000-an, penguatkuasaan agresif dan mobilisasi awam mula mengambil peranan utama. Kes murtad (Lina Joy), pertikaian hak penjagaan anak (Subashini, Shamala), hukuman sebat Syariah, serta fatwa ke atas kumpulan seperti Sisters in Islam menjadikan undang-undang Syariah medan pertempuran nasional. Seperti yang ditunjukkan oleh Tamir Moustafa dalam Constituting Religion (2018), aktor Islamis memainkan peranan penting di sini: mencabar bidang kuasa di mahkamah sambil menggerakkan sentimen awam di luar. Kes-kes ini menjadi titik api moral, menyemarakkan naratif bahawa Islam berada di bawah ancaman dan mengabsahkan tuntutan untuk memperkukuh autoriti Syariah.
Seperti yang dihuraikan Maznah Mohamad dalam Divine Bureaucracy (2020), birokrasi agama Malaysia beroperasi melalui kuasa sirkulatori — peranan bertindih, struktur yang mengesahkan diri sendiri, dan perlindungan perlembagaan. Hasilnya ialah sebuah “birokrasi ilahi”: institusi yang menuntut autoriti bukan melalui demokrasi atau rasionaliti undang-undang, tetapi melalui keutamaan agama yang diperlembagakan dan aura ketuhanan. Apa yang digambarkan sebagai pemerkasaan peradaban akhirnya menjadi infrastruktur perundangan yang menyempitkan kewarganegaraan dan melindungi autoritarianisme di sebalik kesucian agama.
Islamisme sebagai Wahana Neoliberal dengan Pelbagai Wajah
Melihat Islamisme sebagai semata-mata sebuah ideologi bererti mengabaikan sifat kelasnya. Islamisme sentiasa merupakan sebuah projek kelas menengah. Ia lahir daripada kelompok terdidik, urban, dan beraspirasi moden, kelompok yang membayangkan Islam dalam bentuk yang terhormat, profesional dan berstatus. Imaginasi ekonominya pula bersifat neoliberal: kewangan Islam, korporat Islam, profesionalisme.
Seperti yang dihuraikan Patricia Sloane-White dalam Corporate Islam (2017), model yang dibayangkan ialah akumulasi kekayaan, kebajikan, dan filantropi, bukan pengagihan semula atau keadilan ekonomi. Kemiskinan dan ketidaksaksamaan jarang menjadi fokus. Keadilan ekonomi dikecilkan kepada zakat atau filantropi, bukannya perubahan struktural dan pengagihan sumber dan kekayaan. Islamis membayangkan sebuah utopia di mana kekayaan itu “Islami,” statusnya bermoral, dan rasa hormat disandarkan pada kesalehan — sebuah visi yang sangat serasi dengan negara pembangunan Mahathir.
Inilah sebabnya Islamisme dan neoliberalisme bukanlah percanggahan. Mereka saling melengkapi. Islamis menyediakan lapisan moral dan peradaban; neoliberalisme menyediakan jentera pengumpulan modal. Gabungan ini menghasilkan model Islamisasi yang mengukuhkan ketidaksaksamaan sambil menghadirkannya sebagai tertib ketuhanan.
Jika kita memahami bahawa Islamisme itu bersifat peradaban, maka kepelbagaian ekspresinya bukanlah percanggahan tetapi strategi. Oleh itu, pelbagai wajah Islamisme Malaysia boleh ditakrifkan seperti berikut:
- ISMA → supremasi etno-agama secara terang-terangan (ketuanan Islam Melayu).
- PAS → daripada “PAS for All” kepada ketuanan Melayu Islam.
- ABIM → Islam Kosmopolitan: retorik kosmopolitan tetapi tetap berpusatkan keunggulan Islam.
- IKRAM → Negara Rahmah: bahasa belas kasihan tetapi bersandar pada paksi hierarki sama.
- IoK Attasian → pengasingan epistemologi; mengolah semula struktur pengetahuan.
Kesemua ini kelihatan berbeza — eksklusivis, populis, kosmopolitan, intelektual, penuh belas — tetapi berkongsi horizon yang sama: Islam sebagai pusat peradaban yang tidak boleh dipertikaikan.
Inilah sebabnya Malaysia hari ini tidak boleh difahami hanya melalui lensa populisme. Populisme bersifat episodik, bising, dan tidak konsisten — bergantung pada persembahan dan kitaran pilihan raya. Islamisme sebaliknya bersifat peradaban, struktural, dan konsisten. Ia tidak bergantung kepada himpunan atau gelombang populis jangka pendek. Ia meresap ke dalam birokrasi, fatwa, pendidikan dan undang-undang. Ia tidak memerlukan Islamis untuk sentiasa memimpin secara zahir. Kuasanya bersifat pendam, terinstitusi, dan sentiasa direproduksi.
Fenomena Islamisme cair inilah yang menjelaskan ketahanannya. Walaupun nasib pilihan raya berubah, projek peradaban itu berterusan. Ia berterusan dalam:
- Birokrasi yang mengawal moral individu, kehidupan awam dan domestik, dan fatwa yang dijadikan instrumen undang-undang dan tidak boleh dicabar secara akademik atau pentadbiran.
- Kurikulum yang mengakar kuat konsep epistemologi Islam yang dibina atas pandangan alam Islam yang binari.
- Slogan “Islam is the way of life”, yang menjelma dalam obsesi halal, hijab, larangan alkohol, penapisan buku, dan banyak lagi.
- Cara “peradaban Islam” dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dipersoalkan — bukan sebagai ideologi tetapi sebagai kebenaran.
Penutup
Menjelaskan fenomena Islamisme Malaysia sebagai “populisme peradaban Islamis” bererti mencampuradukkan dua logik yang berbeza. Populisme cuma hanya menerangkan selapis permukaan politik Islamis yakni yang bising, episodik, dan oportunis. Tetapi Islamisme bukan sebatas apa yang nampak di permukaan. Islamisme ialah tentang kedalaman sebuah ideologi dan worldview. Ia bersifat peradaban secara reka bentuk, berakar pada epistemologi kebenaran yang mengalir ke dalam politik, birokrasi, undang-undang dan pendidikan.
Islamisasi Mahathir bersifat neoliberal, bukan Islamis, tetapi beliau membina jentera pembirokrasian agama secara besar-besaran. Anwar dan ABIM menyediakan tatabahasa ideologi yang mengakar Islam ke dalam tadbir urus. Islamisasi Ilmu (IoK) al-Attas pula memberikan landasan intelektual dan epistemik yang mentakrifkan semula kebenaran itu sendiri. Birokrasi kemudian berkembang menjadi divine bureaucracy, menghasilkan kuasa beredar tanpa akauntabiliti (Maznah Mohamad) dan autoritarianisme perundangan yang bertunjangkan reka bentuk perlembagaan (Tamir Moustafa). Agenda dan projek Islamisme sebagai projek kelas menengah neoliberal menyelubungi usaha ini dengan bahasa kewangan, profesionalisme dan kesantunan. Pelbagai variasinya meliputi supremasi etno-agama ISMA, populisme majoritarian PAS, kosmopolitanisme ABIM, bahasa rahmah IKRAM, semuanya berputar pada pusat yang sama: Islam sebagai pusat peradaban yang tidak boleh dipertandingkan.
Atas sebab inilah Islamisme tidak boleh diringkaskan sebagai populisme, politik autoritarian, atau logik gerakan sosial. Kerangka-kerangka ini tersilap menilai strategi sebagai asas, dan persembahan sebagai struktur. Projek Islamis ialah projek peradaban: ia membina pengetahuan sebagai kebenaran, kebenaran sebagai tertib, dan tertib sebagai takdir. Ketahanannya tidak terletak pada kitaran pilihan raya atau slogan parti, tetapi pada sifat absolut epistemologinya.
Malaysia hari ini hidup dalam pasca-kehidupan projek itu. Maka cabaran sebenar bukan sekadar menentang Islamisme sebagai politik, tetapi mendedahkan Islamisme sebagai epistemologi peradaban — sebuah epistemologi yang memonopoli kebenaran, mempersenjatai pengetahuan, dan menormalkan autoritarianisme atas nama ketuhanan.
Rujukan:
Abaza, Mona. 2002. Debates on Islam and Knowledge in Malaysia and Egypt: Shifting Worlds. London: RoutledgeCurzon.
al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1993. Islam and Secularism. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
Hew, Wai Weng. 2017. “Consumer Space as Political Space: Liquid Islamism in Malaysia and Indonesia.” In Political Participation in Asia: Defining and Deploying Political Space, edited by Eva Hansson and Meredith L. Weiss, 123–140. London: Routledge.
Moustafa, Tamir. 2018. Constituting Religion: Islam, Liberal Rights, and the Malaysian State. Cambridge: Cambridge University Press.
Maznah Mohamad. 2020. Divine Bureaucracy and Disenchantment of Social Life: A Study of Bureaucratic Islam in Malaysia. Singapore: Palgrave Macmillan.
Shukri, Syaza. 2023. “Islamist Civilizationism in Malaysia.” Religions 14 (2): 209. https://doi.org/10.3390/rel14020209
Sloane-White, Patricia. 2017. Corporate Islam: Sharia and the Modern Workplace. Cambridge: Cambridge University Press.
Tibi, Bassam. 2012. Islamism and Islam. New Haven: Yale University Press.