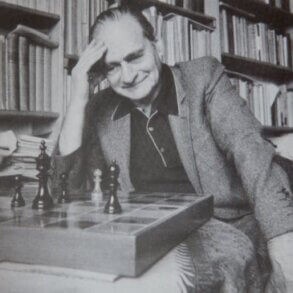Fetisisme Metrik dan Kuantifikasi Pengetahuan dalam Sistem Pendidikan Tinggi Malaysia
Kritik John Smyth terhadap universiti yang digerakkan oleh kuantifikasi metrik dalam bukunya The Toxic University – Zombie Leadership, Academic Rock Stars and Neoliberal Ideology (2017) mempunyai resonans yang mendalam dengan realiti pendidikan tinggi di Malaysia. Sejak awal tahun 2000-an, sistem universiti Malaysia telah melalui satu proses penstrukturan semula yang intensif, sejajar dengan agenda global neoliberalisme pendidikan tinggi. Proses ini dicirikan oleh penekanan agresif terhadap ranking universiti antarabangsa, sasaran output penyelidikan yang boleh diukur, serta mekanisme pembiayaan berasaskan prestasi. Walaupun dasar-dasar ini sering dipertahankan atas nama daya saing global dan kecemerlangan institusi, kesannya terhadap kehidupan akademik, budaya pengetahuan dan fungsi awam universiti jauh lebih kompleks dan problematik.
Dalam kerangka Smyth, kuantifikasi metrik bukan sekadar alat pengurusan neutral, tetapi membentuk suatu rejim nilai yang mentakrifkan semula makna kejayaan akademik. Pengetahuan yang tidak dapat diukur, dikira atau ditukar kepada angka—seperti pengajaran bermakna, pembinaan pemikiran kritikal, atau penyelidikan berakar lokal—cenderung terpinggir. Dalam konteks Malaysia, fetisisme terhadap metrik ini telah menghasilkan satu paradoks: universiti semakin kelihatan “cemerlang” dari sudut penunjuk prestasi antarabangsa, namun semakin rapuh dari segi misi intelektual, kesejahteraan akademik dan relevansi sosial.
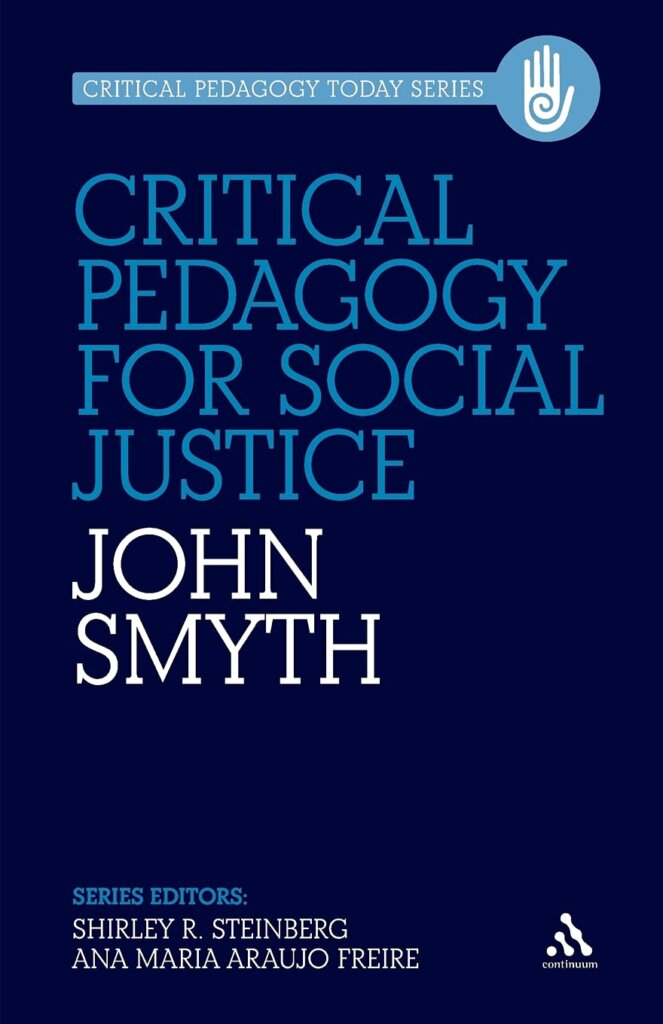
Salah satu manifestasi paling ketara fetisisme metrik dalam pendidikan tinggi Malaysia ialah ketaksuban terhadap ranking universiti global, khususnya QS World University Rankings dan Times Higher Education (THE). Melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015–2025, kerajaan secara eksplisit meletakkan sasaran agar universiti awam tempatan menembusi kelompok 100 teratas dunia. Sasaran ini bukan sekadar simbolik, tetapi diterjemahkan ke dalam pelbagai instrumen dasar: penilaian prestasi institusi, penentuan peruntukan kewangan, serta tekanan langsung terhadap kepimpinan universiti untuk menyusun strategi yang selari dengan metodologi ranking antarabangsa.
Akibatnya, universiti awam di Malaysia semakin menyelaraskan keutamaan mereka kepada indikator yang diiktiraf oleh badan ranking global—seperti bilangan penerbitan berindeks Scopus dan Web of Science (WOS), kadar sitasi, serta kerjasama antarabangsa yang bersifat kuantitatif. Dalam proses ini, persoalan yang lebih mendasar tentang tujuan universiti sering diketepikan. Ranking tidak lagi dilihat sebagai alat perbandingan kasar, tetapi berubah menjadi matlamat itu sendiri. Seperti yang dihujahkan Smyth, apabila metrik menjadi tujuan, universiti mula kehilangan keupayaan untuk menilai dirinya secara kritikal di luar kerangka angka yang telah ditetapkan oleh pasaran global pengetahuan.
Kesan ketaksuban terhadap ranking ini bukan sahaja bersifat institusional, tetapi meresap ke dalam kehidupan harian akademik. Pensyarah di Malaysia semakin dinilai berdasarkan kebolehan mereka menghasilkan artikel dalam jurnal berimpak tinggi, sering kali tanpa mengambil kira kesesuaian penyelidikan tersebut dengan konteks tempatan atau keperluan masyarakat. Pengetahuan yang ditulis dalam Bahasa Melayu, penyelidikan berasaskan komuniti, atau kajian interdisiplin yang sukar diterbitkan dalam jurnal arus perdana antarabangsa sering dianggap sebagai “kurang bernilai” dari sudut kenaikan pangkat dan penilaian prestasi. Fenomena ini mencerminkan apa yang Smyth gambarkan sebagai “korupsi epistemik”, iaitu keadaan di mana nilai pengetahuan ditentukan bukan oleh sumbangan intelektualnya, tetapi oleh kedudukannya dalam pasaran metrik global.
Lebih membimbangkan, budaya kuantifikasi ini turut mengubah imbangan antara penyelidikan dan pengajaran. Dalam sistem yang memberi ganjaran hampir eksklusif kepada output penyelidikan terindeks, pengajaran semakin dilihat sebagai beban pentadbiran, bukan sebagai teras misi universiti. Ramai pensyarah terpaksa mengorbankan masa pedagogi dan bimbingan pelajar demi memenuhi sasaran penerbitan dan geran. Dalam jangka panjang, keadaan ini bukan sahaja menjejaskan kualiti pembelajaran, tetapi turut merosakkan hubungan intelektual antara pensyarah dan mahasiswa—hubungan yang sepatutnya menjadi asas pembentukan warga berfikir dan beretika.
Dalam konteks tenaga kerja akademik, fetisisme metrik juga memperkukuh ketidakamanan dan ketaksamarataan. Pensyarah muda, khususnya mereka yang berstatus kontrak, berada dalam tekanan berterusan untuk membuktikan “nilai pasaran” mereka melalui angka: bilangan artikel, indeks h, dan jumlah geran. Seperti yang diperhatikan Smyth, tekanan ini mewujudkan budaya ketakutan dan kepatuhan, di mana kritik terhadap dasar universiti atau sistem penilaian dianggap berisiko terhadap kelangsungan kerjaya. Di Malaysia, budaya ini diperhebatkan oleh struktur tadbir urus yang berhierarki dan ruang kebebasan akademik yang terhad, menjadikan fetisisme metrik sebagai alat kawalan yang efektif tetapi merosakkan.
Secara keseluruhan, penerapan logik kuantifikasi dalam pendidikan tinggi Malaysia mencerminkan apa yang Smyth istilahkan sebagai universiti beracun—institusi yang kelihatan produktif dari luar, tetapi mengalami hakisan nilai dari dalam. Fetisisme terhadap metrik dan ranking bukan sekadar isu teknikal pengurusan, tetapi persoalan ideologi tentang apa yang dianggap bernilai dalam pendidikan tinggi. Selagi universiti di Malaysia terus menilai kejayaannya melalui angka yang ditetapkan oleh rejim pengetahuan global, selagi itulah pengetahuan tempatan, pedagogi kritikal dan kesejahteraan akademik akan kekal terpinggir.
Oleh itu, cabaran sebenar pendidikan tinggi Malaysia bukanlah sekadar untuk “menaikkan ranking”, tetapi untuk mempersoalkan semula makna kecemerlangan universiti. Seperti yang ditegaskan Smyth, pembebasan universiti daripada toksisiti neoliberal memerlukan keberanian untuk melangkaui metrik, dan mengembalikan universiti kepada peranannya sebagai institusi awam—tempat penghasilan ilmu yang berakar pada keadilan sosial, tanggungjawab intelektual dan keperluan masyarakat.
Pengejaran agresif terhadap ranking universiti global dan metrik prestasi penyelidikan di Malaysia tidak dapat dinafikan telah menghasilkan beberapa kesan yang sering ditonjolkan sebagai kejayaan dasar pendidikan tinggi negara. Dalam tempoh dua dekad yang lalu, universiti-universiti awam Malaysia telah berjaya meningkatkan keterlihatan mereka di peringkat antarabangsa, khususnya melalui penyertaan aktif dalam jaringan penyelidikan global dan kerjasama strategik dengan institusi-institusi terkemuka di Global Utara. Peningkatan ini turut disokong oleh aliran pembiayaan penyelidikan yang lebih besar, terutamanya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM), yang sejajar dengan agenda pembangunan ekonomi berasaskan inovasi dan teknologi tinggi. Insentif penerbitan dan geran berasaskan prestasi telah menyumbang kepada lonjakan kuantitatif dalam output penyelidikan, sekali gus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam statistik global pengeluaran ilmu.
Namun demikian, kejayaan yang diukur melalui angka dan kedudukan ini hadir bersama kos epistemik dan institusional yang semakin ketara. Penekanan berlebihan terhadap metrik sitasi dan indeks impak telah mengherotkan keutamaan akademik, apabila nilai penyelidikan ditentukan hampir sepenuhnya oleh kebolehlihatan dalam pangkalan data antarabangsa, dan bukannya oleh kerelevanan sosial atau sumbangannya kepada masyarakat. Dalam keadaan ini, penyelidikan yang menjawab persoalan mendesak tempatan—seperti ketidaksamarataan sosial, sejarah nasional, budaya, bahasa dan realiti komuniti setempat—sering dianggap kurang strategik kerana sukar menembusi jurnal Barat berimpak tinggi. Tekanan struktural ini mendorong ahli akademik untuk menyesuaikan topik, kerangka teori dan bahkan bahasa penulisan mereka agar selari dengan selera penerbit global, sekali gus mengasingkan universiti daripada konteks sosial yang sepatutnya.
Lebih bermasalah lagi, fetisisme terhadap metrik telah membuka ruang kepada amalan manipulatif yang meremehkan integriti akademik. Beberapa institusi didakwa mengamalkan strategi pengambilan penyelidik “berprofil sitasi tinggi” semata-mata untuk meningkatkan skor ranking, tanpa komitmen jangka panjang terhadap pembangunan akademik atau kualiti pengajaran. Amalan seperti saling memetik secara strategik, penumpuan kepada kuantiti penerbitan berbanding kedalaman intelektual, serta pengutamaan jurnal tertentu demi skor institusi telah menjadi sebahagian daripada budaya persaingan yang tidak sihat. Dalam konteks ini, universiti berisiko berubah daripada institusi pencarian kebenaran kepada organisasi pengurusan angka.
Pengalaman Universiti Malaya sering dijadikan contoh untuk menggambarkan paradoks ini. Pada tahun 2020, peningkatan ketara kedudukan QS universiti tersebut diraikan sebagai kejayaan nasional. Namun, pengkritik berhujah bahawa pencapaian ini tidak semestinya diterjemahkan kepada peningkatan sepadan dalam kualiti pengajaran, pengalaman pembelajaran pelajar, atau kesejahteraan akademik. Sebaliknya, sumber dan perhatian institusi dilihat tertumpu hampir sepenuhnya kepada pemaksimuman output penerbitan dan indikator penyelidikan, menandakan jurang yang semakin melebar antara kecemerlangan metrik dan kecemerlangan pendidikan yang sebenar.
Secara keseluruhan, pengalaman Malaysia menunjukkan bahawa ranking dan metrik bukanlah bersifat neutral atau intrinsik baik. Walaupun ia boleh berfungsi sebagai alat penanda aras dan strategi keterlihatan global, penundukan universiti secara total kepada logik kuantifikasi berisiko menghakis misi awam pendidikan tinggi. Cabaran sebenar bukanlah memilih antara globalisasi atau lokaliti, tetapi membina keseimbangan epistemik yang membolehkan universiti menyumbang kepada ilmu sejagat tanpa mengorbankan tanggungjawab sosial, intelektual dan kebudayaannya sendiri. Tanpa refleksi kritikal terhadap fetisisme metrik ini, universiti di Malaysia berisiko mencapai kecemerlangan yang kelihatan mengagumkan di atas kertas, tetapi rapuh dari segi makna dan tujuan.
Pengejaran agresif terhadap ranking universiti global dan metrik prestasi penyelidikan di Malaysia tidak dapat dinafikan telah menghasilkan beberapa kesan yang sering ditonjolkan sebagai kejayaan dasar pendidikan tinggi negara. Dalam tempoh dua dekad yang lalu, universiti-universiti awam Malaysia telah berjaya meningkatkan keterlihatan mereka di peringkat antarabangsa, khususnya melalui penyertaan aktif dalam jaringan penyelidikan global dan kerjasama strategik dengan institusi-institusi terkemuka di Global Utara. Peningkatan ini turut disokong oleh aliran pembiayaan penyelidikan yang lebih besar, terutamanya dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM), yang sejajar dengan agenda pembangunan ekonomi berasaskan inovasi dan teknologi tinggi. Insentif penerbitan dan geran berasaskan prestasi telah menyumbang kepada lonjakan kuantitatif dalam output penyelidikan, sekali gus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam statistik global pengeluaran ilmu.
Namun demikian, kejayaan yang diukur melalui angka dan kedudukan ini hadir bersama kos epistemik dan institusional yang semakin ketara. Penekanan berlebihan terhadap metrik sitasi dan indeks impak telah mengherotkan keutamaan akademik, apabila nilai penyelidikan ditentukan hampir sepenuhnya oleh kebolehlihatan dalam pangkalan data antarabangsa, dan bukannya oleh kerelevanan sosial atau sumbangannya kepada masyarakat. Dalam keadaan ini, penyelidikan yang menjawab persoalan mendesak tempatan—seperti ketidaksamaan sosial, sejarah nasional, budaya, bahasa dan realiti komuniti setempat—sering dianggap kurang strategik kerana sukar menembusi jurnal Barat berimpak tinggi. Tekanan struktural ini mendorong ahli akademik untuk menyesuaikan topik, kerangka teori dan bahkan bahasa penulisan mereka agar selari dengan selera penerbit global, sekali gus mengasingkan universiti daripada konteks sosial yang sepatutnya dilayan.
Lebih bermasalah lagi, fetisisme terhadap metrik telah membuka ruang kepada amalan manipulatif yang meremehkan integriti akademik. Beberapa institusi didakwa mengamalkan strategi pengambilan penyelidik “berprofil sitasi tinggi” semata-mata untuk meningkatkan skor ranking, tanpa komitmen jangka panjang terhadap pembangunan akademik atau kualiti pengajaran. Amalan seperti saling memetik secara strategik, penumpuan kepada kuantiti penerbitan berbanding kedalaman intelektual, serta pengutamaan jurnal tertentu demi skor institusi telah menjadi sebahagian daripada budaya persaingan yang tidak sihat. Dalam konteks ini, universiti berisiko berubah daripada institusi pencarian kebenaran kepada organisasi pengurusan angka.
Dilema Pendanaan Penyelidikan: Apabila Geran Menjadi Matlamat, Bukan Alat Ilmu
Salah satu kritikan paling tajam yang dikemukakan oleh John Smyth terhadap universiti neoliberal ialah kecenderungan institusi pendidikan tinggi untuk mentakrifkan kecemerlangan akademik hampir sepenuhnya melalui kejayaan memperoleh geran penyelidikan, dan bukannya melalui sumbangan intelektual atau nilai keilmuan itu sendiri. Dalam kerangka ini, penyelidikan tidak lagi didorong oleh rasa ingin tahu ilmiah, keperluan masyarakat, atau tanggungjawab epistemik, sebaliknya menjadi aktiviti strategik yang tertakluk kepada logik persaingan, pengurusan prestasi, dan pulangan pelaburan. Fenomena yang sama dapat diperhatikan dengan jelas dalam sistem pendidikan tinggi Malaysia, di mana pendanaan penyelidikan telah menjadi paksi utama penilaian institusi dan individu akademik.
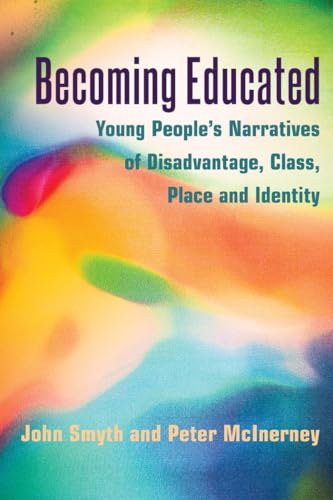
Di Malaysia, orientasi terhadap geran penyelidikan ini dimediasi melalui beberapa mekanisme dasar dan institusi yang saling berkait. Sistem penilaian seperti Malaysia Research Assessment (MyRA) menilai prestasi universiti berdasarkan kuantiti output penyelidikan, bilangan paten, kadar pengkomersialan, serta jumlah dana penyelidikan yang berjaya diperoleh. Dalam masa yang sama, skim geran kerajaan—seperti Fundamental Research Grant Scheme (FRGS), Prototype Research Grant Scheme (PRGS), Long-Term Research Grant Scheme (LRGS) dan Transdisciplinary Research Grant Scheme (TRGS)—secara struktural memberi keutamaan kepada bidang yang berpotensi menghasilkan inovasi teknikal, produk komersial, atau impak pasaran, khususnya dalam sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik (STEM). Penekanan ini diperkuatkan lagi apabila kejayaan memperoleh geran berskala besar dijadikan syarat penting dalam proses kenaikan pangkat dan pengesahan jawatan akademik, sekali gus menjadikan geran sebagai mata wang simbolik utama dalam hierarki akademik.
Pendanaan berasaskan metrik ini sememangnya telah menghasilkan beberapa kesan yang sering dirujuk sebagai pencapaian nasional. Malaysia telah mencatat peningkatan dalam bilangan paten, hasil inovasi teknologi, serta aktiviti penyelidikan dalam bidang seperti kecerdasan buatan, bioteknologi dan tenaga boleh baharu. Keupayaan universiti untuk menarik dana penyelidikan dan membina kerjasama dengan industri turut dipersembahkan sebagai petunjuk kematangan ekosistem penyelidikan negara dan kesediaannya untuk bersaing dalam ekonomi berasaskan pengetahuan global. Dari sudut ini, sistem pendanaan sedia ada sering dipertahankan atas alasan kecekapan, kebolehukuran dan sumbangan langsung kepada pertumbuhan ekonomi.
Namun demikian, di sebalik naratif kejayaan ini, wujud kesan sampingan yang semakin membebankan kehidupan akademik dan mengherotkan orientasi penyelidikan. Tekanan untuk mendapatkan geran telah mengalihkan masa dan tenaga ahli akademik daripada kerja intelektual substantif kepada aktiviti pentadbiran—menulis kertas cadangan berulang kali, memenuhi keperluan pelaporan, dan menyesuaikan idea penyelidikan agar selari dengan keutamaan pembiaya. Dalam banyak kes, kejayaan penyelidikan tidak lagi diukur berdasarkan kualiti hujah, ketelitian metodologi atau sumbangan teorinya, tetapi berdasarkan kebolehan seorang ahli akademik dalam “menjual” projek mereka dalam bahasa impak, inovasi dan kebolehpasaran.
Lebih membimbangkan, logik pendanaan berasaskan potensi komersial ini telah meminggirkan kepentingan awam sebagai asas penilaian penyelidikan. Isu-isu sosial yang mendesak—seperti ketidaksamaan pendidikan, kemiskinan bandar dan luar bandar, warisan budaya, bahasa, sejarah tempatan, atau pengetahuan pribumi—sering dianggap tidak strategik kerana tidak menjanjikan pulangan ekonomi segera. Akibatnya, bidang kemanusiaan dan sains sosial terus berada dalam kedudukan marginal dari segi pembiayaan, walaupun bidang-bidang inilah yang menyediakan kerangka kritikal untuk memahami identiti nasional, kohesi sosial, dan cabaran pembangunan jangka panjang.
Situasi ini dapat dilihat dengan jelas dalam konteks penyelidikan terhadap warisan manuskrip Melayu. Khazanah intelektual ini merangkumi pelbagai disiplin—daripada falsafah, undang-undang, perubatan tradisional, sejarah, hingga kosmologi—namun masih kurang diterokai secara sistematik. Walaupun penyelidikan dalam bidang ini berpotensi besar untuk memperkayakan pemahaman tentang sejarah intelektual Alam Melayu dan menyumbang kepada pembinaan pengetahuan alternatif yang berakar tempatan, ia sering menerima pembiayaan yang jauh lebih kecil berbanding penyelidikan bioteknologi atau kecerdasan buatan. Ketiadaan potensi komersial segera menjadikan bidang ini hampir tidak kelihatan dalam ekosistem geran nasional, sekali gus mencerminkan bagaimana nilai ilmu ditentukan oleh logik pasaran, bukan kepentingan kebudayaan atau epistemik.
Secara keseluruhan, dilema pendanaan penyelidikan di Malaysia memperlihatkan pergeseran mendalam daripada universiti sebagai ruang pencarian ilmu kepada universiti sebagai organisasi pengurusan projek. Seperti yang dihujahkan oleh Smyth, apabila geran menjadi matlamat dan bukan alat, penyelidikan kehilangan orientasi moral dan intelektualnya. Cabaran utama pendidikan tinggi Malaysia hari ini bukanlah menolak pendanaan atau penyelidikan berimpak teknologi, tetapi membina semula keseimbangan epistemik—di mana penyelidikan dinilai bukan sahaja melalui jumlah dana dan pulangan pasaran, tetapi melalui sumbangannya kepada masyarakat, budaya, dan masa depan pengetahuan negara.
Kacau bilau dan Pengurangan Tenaga Kerja Akademik dalam Pendidikan Tinggi Malaysia
Salah satu implikasi paling ketara daripada fetisisme metrik dalam pendidikan tinggi ialah kacau bilau kerja akademik, iaitu proses di mana keselamatan pekerjaan, autonomi profesional dan kesejahteraan intelektual semakin terhakis atas nama kecekapan, fleksibiliti dan prestasi yang boleh diukur. Sejajar dengan kritikan John Smyth terhadap universiti neoliberal, institusi pengajian tinggi di Malaysia semakin mengadaptasi model pengurusan sumber manusia yang berasaskan kontrak, sementara, dan bersyarat, yang mengutamakan hasil penyelidikan serta kepatuhan terhadap indikator prestasi berbanding pembangunan kerjaya akademik jangka panjang dan kebebasan ilmiah.

Dalam konteks Malaysia, trend ini jelas dapat diperhatikan melalui peningkatan ketara dalam pengambilan ahli akademik berstatus kontrak, khususnya dalam kalangan sarjana muda dan peringkat awal kerjaya. Berbeza dengan model tradisional yang menyediakan jawatan tetap dengan laluan kenaikan pangkat yang relatif jelas, ramai pensyarah kini diambil bekerja melalui kontrak jangka pendek yang tertakluk kepada penilaian prestasi tahunan. Penilaian ini lazimnya berfokus kepada bilangan penerbitan dalam jurnal berindeks Scopus atau ISI, kejayaan memperoleh geran penyelidikan, serta sumbangan kepada metrik institusi. Keadaan ini mewujudkan persekitaran kerja yang tidak stabil, di mana masa depan kerjaya akademik sentiasa bergantung kepada pencapaian kuantitatif yang sering kali berada di luar kawalan individu.
Dalam masa yang sama, beban kerja akademik menjadi semakin tidak seimbang. Ramai pensyarah kontrak dan junior dikehendaki memikul beban pengajaran yang berat—mengendalikan beberapa kursus dalam satu semester dan pada masa yang sama dituntut untuk menghasilkan penyelidikan berimpak tinggi dalam tempoh yang singkat. Ketegangan antara pengajaran dan penyelidikan ini bukan sahaja menimbulkan keletihan profesional, tetapi juga mencerminkan bagaimana pengajaran semakin dianggap sebagai kewajipan sekunder berbanding aktiviti penyelidikan yang menjana metrik dan reputasi institusi. Di universiti swasta pula, kebergantungan terhadap pensyarah sambilan bergaji rendah semakin ketara, di mana ramai daripada mereka tidak menikmati perlindungan kebajikan, keselamatan pekerjaan atau peluang pembangunan profesional yang bermakna.
Penyokong model ini sering berhujah bahawa sistem kontrak membuka lebih banyak peluang kepada graduan PhD untuk memasuki dunia akademik, sekali gus mengurangkan pengangguran dalam kalangan pemegang ijazah kedoktoran. Terdapat juga kes di mana jawatan kontrak akhirnya membawa kepada pelantikan tetap, terutamanya bagi individu yang berjaya memenuhi atau melangkaui sasaran prestasi institusi. Namun, manfaat ini bersifat terhad dan tidak mengimbangi kesan struktural yang lebih luas terhadap budaya akademik dan kesejahteraan tenaga kerja universiti.
Kesan negatif suasana kacau bilau akademik semakin jelas dan membimbangkan. Ketidakpastian pekerjaan yang berpanjangan, digabungkan dengan tekanan untuk sentiasa “berprestasi”, telah menyumbang kepada peningkatan masalah kesihatan mental dalam kalangan ahli akademik peringkat awal kerjaya. Tekanan ini bukan sahaja bersifat individu, tetapi berakar dalam struktur institusi yang menormalisasikan kerja berlebihan, persaingan berterusan dan rasa takut terhadap kegagalan. Selain itu, keadaan kerja yang tidak stabil dan peluang kemajuan kerjaya yang terhad telah mendorong fenomena penghijrahan bakat, apabila sebahagian ahli akademik terbaik memilih untuk berhijrah ke universiti luar negara yang menawarkan laluan kerjaya lebih jelas, sokongan penyelidikan yang konsisten dan jaminan pekerjaan yang lebih baik.
Suasana kacau bilau ini turut memberi kesan langsung terhadap kualiti pengajaran dan pengalaman pembelajaran pelajar. Apabila ahli fakulti terpaksa mengutamakan penerbitan dan permohonan geran demi kelangsungan kerjaya mereka, penglibatan pedagogi—seperti bimbingan pelajar, inovasi pengajaran, dan pembangunan kurikulum—sering diketepikan. Dalam jangka panjang, keadaan ini menghakis peranan universiti sebagai ruang pembelajaran yang bermakna dan memperdalam jurang antara misi pendidikan dengan realiti pengurusan institusi.
Tidak menghairankan jika universiti-universiti awam utama seperti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Universiti Malaya (UM) dan Universiti Sains Malaysia (USM) telah menyaksikan protes dan tuntutan daripada pensyarah kontrak yang mendesak gaji lebih adil serta kestabilan pekerjaan. Walau bagaimanapun, pihak pengurusan universiti sering mempertahankan amalan ini dengan merujuk kepada pemotongan dana kerajaan dan kekangan kewangan institusi. Justifikasi ini, walaupun mempunyai asas material, tidak menafikan hakikat bahawa beban penyesuaian terhadap krisis pembiayaan telah dipindahkan secara tidak seimbang kepada tenaga kerja akademik, khususnya golongan paling rentan.
Secara keseluruhan, pengurangan dan kacau bilau tenaga kerja akademik di Malaysia memperlihatkan bagaimana fetisisme metrik bukan sahaja membentuk apa yang dihasilkan oleh universiti, tetapi juga siapa yang mampu bertahan di dalamnya. Seperti yang ditegaskan oleh Smyth, universiti yang membina kecemerlangan di atas ketidakpastian dan eksploitasi tenaga kerja akhirnya menjejaskan asas moral dan intelektualnya sendiri. Cabaran pendidikan tinggi Malaysia pada masa hadapan adalah untuk membina semula sistem pekerjaan akademik yang berasaskan keadilan, kestabilan dan penghargaan terhadap kerja pengajaran dan penyelidikan sebagai amalan intelektual, bukan sekadar pengeluaran metrik.
Penyusutan Nilai Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pendidikan Tinggi Malaysia
Salah satu kebimbangan utama yang diketengahkan oleh John Smyth dalam kritikannya terhadap universiti neoliberal ialah kemerosotan kedudukan pengajaran dalam hierarki nilai institusi pengajian tinggi. Dalam sistem yang semakin dikuasai oleh fetisisme metrik, pengajaran tidak lagi dianggap sebagai teras misi universiti, sebaliknya direduksi kepada fungsi sokongan yang perlu “diurus” agar tidak mengganggu produktiviti penyelidikan. Fenomena ini mempunyai gema yang jelas dalam konteks pendidikan tinggi Malaysia, di mana pensyarah semakin dinilai dan dihargai berdasarkan output penyelidikan yang boleh dikuantifikasikan, berbanding sumbangan pedagogi yang bersifat kualitatif dan relasional.
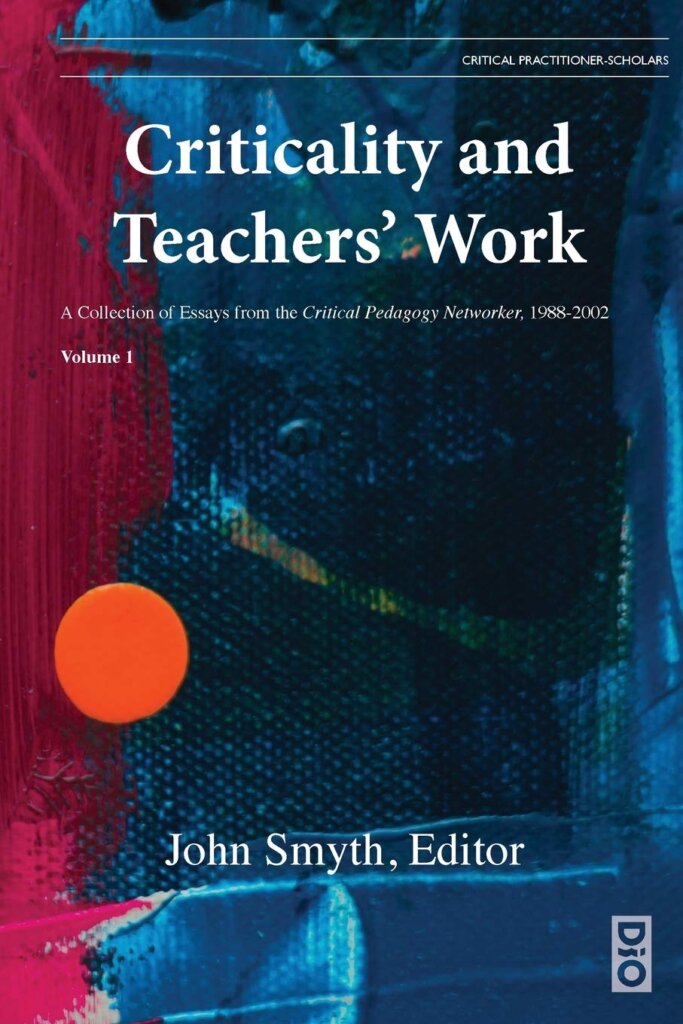
Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, berlaku peralihan ketara dalam definisi peranan pensyarah universiti di Malaysia. Kriteria penilaian prestasi, kenaikan pangkat dan pengiktirafan institusi semakin tertumpu kepada bilangan penerbitan, sitasi, serta kejayaan memperoleh geran penyelidikan. Walaupun pengajaran masih diiktiraf secara formal sebagai tanggungjawab utama pensyarah, realitinya ia jarang membawa ganjaran simbolik atau material yang setara dengan pencapaian penyelidikan. Akibatnya, pensyarah yang memikul beban pengajaran tinggi—terutamanya dalam program sarjana muda—sering berada dalam kedudukan yang tidak menguntungkan dalam laluan kerjaya akademik, walaupun mereka memainkan peranan penting dalam pembentukan intelektual pelajar.
Dalam kerangka pengurusan universiti yang berorientasikan prestasi, Penilaian Pengajaran oleh Pelajar (Student Evaluation of Teaching, SET) sering digunakan sebagai indikator utama kualiti pengajaran. Namun, seperti yang dikritik secara meluas dalam literatur pendidikan tinggi, metrik ini mempunyai kelemahan metodologi yang serius. SET cenderung dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran seperti populariti pensyarah, tahap kesukaran kursus, atau jangkaan gred, dan bukannya keberkesanan pedagogi sebenar. Dalam konteks Malaysia, kebergantungan berlebihan terhadap SET bukan sahaja gagal menangkap kerumitan proses pembelajaran, tetapi juga berpotensi menggalakkan amalan pedagogi yang bersifat oportunistik dan berorientasikan kepuasan segera.
Dari sudut tertentu, penekanan terhadap penyelidikan tidak semestinya membawa kesan negatif secara mutlak kepada pengalaman pembelajaran pelajar. Pengajaran yang berasaskan penyelidikan berpotensi memperkayakan kandungan kurikulum dengan pengetahuan terkini dan pendedahan kepada perdebatan akademik mutakhir. Pelajar juga berpeluang berinteraksi dengan pensyarah yang aktif dalam bidang kepakaran mereka, sekali gus memperluas horizon intelektual dan kebolehan analitikal. Namun, potensi ini hanya dapat direalisasikan jika terdapat keseimbangan yang sihat antara tuntutan penyelidikan dan komitmen pedagogi.
Sebaliknya, dalam banyak keadaan, dominasi agenda penyelidikan telah menghasilkan kesan sampingan yang menjejaskan kualiti pembelajaran. Saiz kelas yang semakin besar, terutamanya di universiti awam, mengurangkan peluang untuk bimbingan individu, perbincangan mendalam dan maklum balas formatif yang bermakna. Pensyarah yang dibebani dengan tanggungjawab penyelidikan dan pentadbiran sering tidak mempunyai masa atau tenaga untuk membangunkan pedagogi inovatif yang memupuk pemikiran kritis. Akibatnya, banyak kursus bergantung kepada kaedah pengajaran tradisional yang menekankan hafalan dan penilaian berasaskan peperiksaan, berbanding pembelajaran reflektif dan analitikal yang diperlukan dalam masyarakat kompleks dan demokratik.
Tekanan terhadap kualiti pengajaran menjadi lebih ketara dalam konteks universiti swasta di Malaysia. Dalam persekitaran yang sangat kompetitif dan berorientasikan pasaran, kepuasan pelajar sering ditafsirkan sebagai indikator utama kejayaan institusi. Dalam keadaan ini, pensyarah—khususnya yang berstatus kontrak—boleh berhadapan tekanan tidak langsung untuk melonggarkan standard akademik demi memperoleh penilaian pelajar yang lebih tinggi, memandangkan keputusan tersebut berkait rapat dengan pembaharuan kontrak atau kesinambungan pekerjaan mereka. Amalan sedemikian bukan sahaja mencairkan integriti akademik, tetapi juga mereduksi pendidikan tinggi kepada transaksi perkhidmatan, selari dengan apa yang disifatkan Smyth sebagai “komodifikasi pedagogi”.
Secara keseluruhan, penyusutan nilai pengajaran dalam pendidikan tinggi Malaysia mencerminkan masalah struktur yang lebih mendalam dalam tadbir urus universiti neoliberal. Apabila pengajaran dinilai melalui metrik yang sempit dan dipinggirkan dalam sistem ganjaran institusi, misi pendidikan universiti sebagai ruang pembentukan pemikiran kritis dan pembangunan insan menjadi terancam. Seperti yang ditegaskan oleh Smyth, universiti yang mengorbankan pengajaran demi mengejar kecemerlangan metrik akhirnya bukan sahaja menjejaskan pengalaman pelajar, tetapi juga menghakis legitimasi moral dan sosial institusi itu sendiri. Cabaran utama pendidikan tinggi Malaysia ialah untuk memulihkan keseimbangan antara penyelidikan dan pengajaran, serta mengiktiraf pedagogi sebagai teras kepada fungsi awam universiti, bukannya sebagai beban yang perlu diminimumkan.
Merebut Kembali Integriti Akademik di Malaysia: Ke Arah Pendekatan Alternatif
Dalam The Toxic University, John Smyth menegaskan bahawa universiti yang digerakkan secara eksklusif oleh metrik bukan sekadar mengalami kecacatan pengurusan, tetapi sedang berdepan krisis etika dan epistemik. Kritikan ini amat relevan dalam konteks pendidikan tinggi Malaysia, di mana logik ranking, kuantifikasi prestasi dan penilaian berasaskan hasil telah menjadi asas utama tadbir urus universiti. Justeru, usaha untuk merebut kembali integriti akademik memerlukan bukan sahaja pembaikan teknikal, tetapi perubahan paradigma yang lebih menyeluruh terhadap cara universiti menilai nilai, kecemerlangan dan sumbangan ilmu.
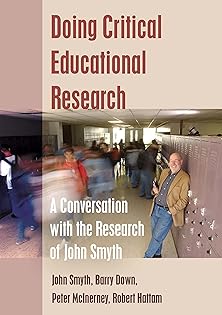
Salah satu langkah penting ke arah pembaharuan ialah pembinaan sistem penilaian akademik yang lebih seimbang dan berlapis. Dalam sistem sedia ada, penerbitan dalam jurnal yang diindeks oleh Scopus dan ISI sering dijadikan ukuran dominan kecemerlangan akademik, sekali gus meminggirkan bentuk kesarjanaan lain yang mempunyai nilai sosial dan intelektual yang signifikan. Universiti di Malaysia perlu mengiktiraf penyelidikan tempatan yang berasaskan konteks masyarakat, kesarjanaan dalam bahasa kebangsaan, penulisan dasar awam, serta penglibatan komuniti sebagai sumbangan ilmiah yang sah dan bernilai. Pendekatan ini bukan sahaja akan memperkayakan ekologi pengetahuan nasional, tetapi juga mengurangkan kebergantungan kepada epistemologi dan agenda penerbitan Global Utara.
Seiring dengan itu, pemerkasaan semula bidang sains sosial dan kemanusiaan perlu dilihat sebagai keperluan strategik, bukannya beban sampingan dalam sistem pendidikan tinggi. Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, keutamaan pembiayaan penyelidikan di Malaysia telah tertumpu kepada bidang STEM, inovasi dan komersialisasi, manakala kajian budaya, sejarah, pendidikan, dan isu sosial menerima peruntukan yang terhad. Keadaan ini mencerminkan kefahaman sempit tentang “impak”, yang sering disamakan dengan pulangan ekonomi jangka pendek. Hakikatnya, cabaran besar negara—seperti ketidaksamaan sosial, hubungan etnik, krisis demokrasi dan kelestarian alam—menuntut sumbangan mendalam daripada sains sosial dan kemanusiaan. Tanpa pemulihan kedudukan bidang-bidang ini, universiti berisiko kehilangan peranannya sebagai institusi awam yang kritikal dan reflektif.
Selain pembaharuan epistemik, isu integriti akademik juga berkait rapat dengan struktur kuasa dan kondisi kerja dalam universiti. Dalam hal ini, pengukuhan kesatuan dan persatuan akademik merupakan elemen penting untuk mengekang kesan kasualisasi tenaga akademik dan pengurusan autoritarian. Seperti yang ditunjukkan oleh Smyth, tenaga akademik yang berada dalam keadaan tidak menentu dari segi pekerjaan sukar untuk mempertahankan kebebasan intelektual atau mencabar dasar institusi yang bermasalah. Di Malaysia, persatuan pensyarah dan badan profesional perlu memainkan peranan yang lebih aktif dan kolektif dalam memperjuangkan keadilan pekerjaan, ketelusan kenaikan pangkat, serta perlindungan terhadap kebebasan akademik. Tanpa suara kolektif yang berfungsi, universiti akan terus ditadbir melalui logik kepatuhan dan ketakutan.
Pembaharuan juga perlu merangkumi pemisahan yang lebih jelas antara penilaian pengajaran dan penilaian penyelidikan. Dalam sistem semasa, kualiti pengajaran sering dinilai secara dangkal melalui instrumen seperti tinjauan kepuasan pelajar, yang tidak semestinya mencerminkan keberkesanan pedagogi atau pencapaian pembelajaran jangka panjang. Universiti perlu membangunkan mekanisme penilaian pengajaran yang lebih bermakna, termasuk penilaian rakan sejawat, refleksi pedagogi, dan penglibatan pelajar dalam proses pembelajaran secara substantif. Dengan memisahkan pengiktirafan pengajaran daripada tekanan metrik penyelidikan, universiti dapat mengembalikan martabat pedagogi sebagai teras misi pendidikan tinggi.
Kesimpulan: Ke Arah Sistem Universiti Malaysia yang Lebih Holistik dan Beretika
Secara keseluruhan, fetisisme terhadap metrik telah membentuk semula landskap pendidikan tinggi Malaysia dengan meletakkan keutamaan kepada ranking global, kejayaan mendapatkan geran, dan pengeluaran penerbitan, sering kali dengan mengorbankan pembelajaran holistik, kesejahteraan tenaga akademik, dan tanggungjawab sosial universiti. Walaupun dasar-dasar ini telah membawa peningkatan tertentu dari segi keterlihatan dan kapasiti institusi, ia juga telah menghasilkan penyelewengan serius dalam amalan akademik, termasuk kacau bilau pekerjaan, penyusutan nilai pengajaran, dan peminggiran pengetahuan tempatan.
Untuk merebut kembali peranan universiti sebagai institusi awam yang bermakna, semua pihak berkepentingan—termasuk pembuat dasar, pentadbir universiti, ahli akademik dan pelajar—perlu memperjuangkan model pendidikan tinggi yang lebih holistik dan beretika. Model ini harus menghargai keingintahuan intelektual, relevansi sosial, keadilan epistemik dan kebebasan akademik, bukannya terikat secara sempit kepada ranking berangka dan bilangan sitasi. Seperti yang diingatkan oleh Smyth, masa depan universiti tidak ditentukan oleh sejauh mana ia mematuhi logik pasaran, tetapi oleh keberaniannya untuk mempertahankan makna ilmu, pendidikan dan tanggungjawab terhadap masyarakat.
Rujukan
Smyth, John (2017) The Toxic University – Zombie Leadership, Academic Rock Stars and Neoliberal Ideology, Huddersfield, UK : Palgrave Macmillan