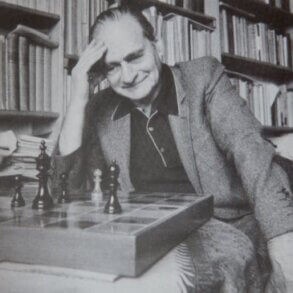Keputusan Mahkamah Persekutuan yang memihak kepada Sisters in Islam mencetuskan gelombang reaksi balas. Respons daripada aktor negara dan Islamis mendedahkan ia bukanlah usaha mempertahankan demokrasi Malaysia dan prinsip hak kenegaraan buat warganya, tetapi ia adalah manifestasi kepanikan untuk membentengi autoriti fatwa sebagai sebuah kuasa yang tidak boleh dituntut akauntabilitinya dalam mekanisme demokrasi Malaysia dan dipersoalkan etika moralnya.
Pengenalan: Keputusan SIS sebagai Ujian Kertas Litmus Demokrasi Malaysia
Pada 19 Jun 2025, Mahkamah Persekutuan Malaysia memutuskan memihak kepada Sisters in Islam (SIS) Forum (Malaysia), dengan menegaskan bahawa fatwa Selangor tahun 2014 yang mengisytiharkan liberalisme dan pluralisme sebagai sesat tidak boleh dikuatkuasakan terhadap sebuah syarikat berdaftar. Keputusan ini menegaskan satu had batas perlembagaan yang amat penting: fatwa tidak boleh diperluaskan kepada entiti korporat. Ini bukan sekadar isu teknikal, tetapi soal perlindungan hak sivil. Dengan menarik garis yang jelas antara autoriti agama dan undang-undang perlembagaan, Mahkamah Persekutuan menandakan satu langkah ke hadapan yang signifikan bagi demokrasi dan perlembagaan Malaysia.
Namun begitu, reaksi yang menyusul, baik daripada pihak berkuasa agama negeri, aktor Islamis, dan pemimpin negara, ia mendedahkan sesuatu yang lebih mendalam dan sifatnya struktural dan institusional. Daripada membincangkan persoalan etika atau perundangan, kesemuanya bertumpu pada satu perkara: mempertahankan autoriti fatwa sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh. Momen kepanikan ini menonjolkan had demokrasi Islamis, iaitu keadaan di mana penyertaan dalam institusi demokratik menyembunyikan komitmen yang lebih mendalam terhadap supremasi agama. Oleh itu, keputusan SIS membuka satu ruang kritikal untuk memahami bagaimana birokrasi Ilahi Malaysia dan gerakan Islamis bertindak apabila berhadapan dengan kekangan perundangan dan benteng kehakiman.
Bayang-bayang Panjang Islamisasi
Untuk memahami mengapa keputusan SIS mencetuskan reaksi yang begitu visceral, adalah perlu untuk meletakkan autoriti fatwa dalam trajektori Islamisasi Malaysia yang lebih panjang sejak projek Islamisasi yang dilakukan oleh negara pada tahun 1980-an. Sejak 1980-an, mahkamah syariah memperluaskan bidang kuasa ke atas undang-undang keluarga, penguatkuasaan moral, dan status peribadi, manakala jabatan agama negeri memperoleh autoriti ke atas semakin banyak urusan sosial dan budaya. Menjelang tahun 2000-an, fatwa tidak lagi sekadar pandangan nasihat, tetapi memperoleh kuasa separa perundangan. Ia bukan sahaja membentuk tingkah laku individu, malah mengawal penerbitan, media, dan entiti korporat.
Maznah Mohamad, dalam Divine Bureaucracy (2020), menghuraikan fenomena ini sebagai satu sistem kuasa beredar: bidang kuasa yang bertindih di mana autoriti birokrasi dan agama saling memperkukuh, menghasilkan kuasa tanpa akauntabiliti. Fatwa berada di teras mesin ini—dipersembahkan sebagai berpaksikan ketuhanan, namun dikuatkuasakan melalui sistem birokrasi moden. Percantuman antara ketuhanan dan birokrasi ini menjadikan fatwa kebal daripada kritikan, walaupun ia membawa implikasi sosial dan perundangan yang mengikat.
Struktur institusi ini sejajar dengan apa yang Bassam Tibi sebut sebagai Islamisme institusional dalam bukunya Islamism and Islam. Berbeza dengan Islamisme jihadis atau militan yang menggunakan keganasan, Islamisme institusional menyusup dan menempel ke dalam struktur negara seperti parlimen, NGO, mahkamah, dan birokrasi, untuk mencapai tujuan yang sama: pensakralan politik dan tuntutan bahawa kedaulatan bukan milik rakyat tetapi milik Tuhan (hakimiyyat Allah). Tibi menegaskan bahawa apa yang sering disebut sebagai “Islamisme sederhana” atau moderat tidak berbeza secara substantif; penerimaan mereka terhadap bentuk demokrasi bersifat taktikal, bukan berprinsip. Dengan menyertai sistem demokrasi, Islamis institusional memperoleh legitimasi, namun projek ideologi mereka kekal; iaitu melindungi autoriti agama daripada pertanggungjawaban manusia dan tidak boleh dipersoalkan. Autoriti agama adalah manifestasi hakimiyat Allah dalam wajah institusi moden.
Dalam konteks Malaysia, pertembungan antara birokrasi Ilahi dan Islamisme institusional menjelaskan mengapa keputusan fatwa SIS begitu mengundang kegusaran. Batas kehakiman terhadap autoriti fatwa dibaca bukan sebagai perlindungan perlembagaan pada hak sivil di Malaysia, tetapi sebagai ancaman terhadap keseluruhan binaan Islamisasi Malaysia.
Reaksi Balas: Kesepakatan Merentas Institusi dan Gerakan
Rentetan respons terhadap keputusan SIS, walaupun berbeza nada, bertemu pada satu tuntutan utama: pemeliharaan autoriti fatwa. Respons pihak berkuasa agama menggambarkan seolah-olah institusi fatwa berada di bawah ancaman kerana SIS didakwa mencabar bidang kuasanya, dan tindakan tersebut dianggap tidak boleh diterima. Mereka menegaskan legitimasi mereka untuk mengeluarkan fatwa secara sewenang-wenangnya berkaitan urusan umat Islam.
Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) dan Sultan Selangor menyuarakan kekecewaan, dengan menegaskan bahawa walaupun fatwa itu tidak terpakai kepada entiti korporat, ia tetap sah ke atas individu. MAIS mendakwa bahawa keputusan mahkamah telah mewujudkan kelompongan yang membolehkan kumpulan “sesat” bersembunyi. Sultan Selangor, selaku Ketua Agama Islam negeri, menggesa SIS supaya menggugurkan perkataan “Islam” daripada namanya untuk mengelakkan kekeliruan. Langkah ini membingkai had kehakiman sebagai penghinaan simbolik, menukar keputusan perlembagaan menjadi persoalan kesetiaan agama.
Mufti Selangor mengukuhkan pembingkaian ini dengan melabelkan SIS sebagai gerakan “seperti kultus”. Ini bukan cercaan rambang, tetapi satu strategi epistemik: menafikan status SIS sebagai aktor intelektual dan seterusnya menegaskan fatwa sebagai kebenaran mutlak. Hakikatnya, rekod SIS bercanggah dengan gambaran ini. Sejak menubuhkan Musawah pada 2009, SIS telah membina rangkaian transnasional kesarjanaan feminis Islam. Ia merupakan rakan aktif Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang dilancarkan pada 2017 dan menghimpunkan lebih seribu ulama perempuan untuk membahaskan fiqh dan keadilan. Korpus kerja SIS, merangkumi penerbitan, latihan perundangan, kerja produksi ilmiah, dan ijtihad berasaskan maqasid, jelas berakar pada tradisi intelektual, bukannya seperti kumpulan kultus yang anti-intelektual dan tidak mahu engage dengan tradisi keilmuan Islam. Keengganan untuk mengiktiraf hal ini mencerminkan strategi delegitimasi: dengan mereduksi SIS kepada “penyelewengan”, aktor Islamis mempertahankan fatwa tanpa perlu berdepan dengan kesahihan etikanya.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) mengambil nada yang lebih berdamai, dengan menghormati proses kehakiman sambil menegaskan bahawa fatwa kekal penting sebagai panduan umat Islam. Beliau menyeru kerjasama yang lebih mantap antara kehakiman, legislatif, dan institusi agama demi mengekalkan kewibawaan institusi fatwa. Bahkan di peringkat Persekutuan, mesej terasnya sama: kekangan kehakiman tidak boleh diterjemahkan sebagai pelemahan autoriti agama.
Gerakan Islamis: Tiga Ragam Respons
Respons gerakan Islamis boleh dibahagikan kepada tiga ragam utama: sayap kanan ekstrem, golongan sederhana, dan pakatan koalisi.
- Islamis kanan ekstrem (WAFIQ/ISMA).
WAFIQ, yang berkait dengan ISMA, menyerang SIS secara langsung melalui lensa gender. SIS digambarkan sebagai “kuda Trojan” liberalisme dan feminisme, sementara feminisme Islam ditolak sepenuhnya sebagai penyelewengan Barat. Retorik ini memberi amaran kepada umat Islam tentang advokasi hak wanita yang “palsu” dan menuntut tindakan negara yang lebih keras terhadap penerbitan dan forum SIS. Pendekatan kepanikan moral ini bertujuan menghalang agenda keadilan gender SIS dengan memposisikan WAFIQ sebagai satu-satunya penjaga keaslian kewanitaan Islam. - Islamis sederhana (ABIM dan IKRAM).
Respons ABIM mendedahkan kepanikan dalam bentuk berbeza. Sebagai organisasi Islamis terawal yang membina infrastruktur aktivisme perundangan Islam, ABIM sekian lama memperluaskan bidang kuasa syariah melalui peguam yang bersekutu dengannya. Kenyataan 2025 mereka tidak menumpukan teologi, tetapi autoriti institusi—memberi amaran bahawa keputusan ini boleh melemahkan fatwa dan menggugat sistem perundangan dual Malaysia. Mereka menuntut pengiktirafan persekutuan yang lebih jelas terhadap fatwa, pindaan undang-undang untuk mengukuhkan institusi agama, dan turut menyeru campur tangan Majlis Raja-Raja bagi mempertahankan supremasi Islam.
IKRAM pula membungkus pertahanan fatwa dengan retorik rahmah. Kenyataannya menggambarkan Islam sebagai sistem syumul pentadbiran dan moral, menyamakan SIS dengan kumpulan kultus seperti GISB, dan memberi amaran tentang eksploitasi “kelompongan korporat”. Walaupun menjanjikan dialog lunak dan pendekatan inklusif, IKRAM tetap mendesak pembaharuan undang-undang bagi meluaskan pengawasan syariah. Pembungkusan yang lebih lembut ini menunjukkan bagaimana Islamis sederhana mengekalkan teras autoritarianisme agama sambil menampilkan diri sebagai pembaharu berperikemanusiaan.
- Pakatan Koalisi Islamis
Koalisi Islamis seperti Himpunan Gerakan Islam Malaysia (HIKAM)—yang merangkumi ABIM, IKRAM, WADAH, dan HALUAN—memperlihatkan kuasa penyatuan isu fatwa. Kenyataan bersama mereka menyokong gesaan Sultan agar SIS menggugurkan perkataan “Islam”, menegaskan fatwa sebagai penting untuk melindungi akidah dan tertib moral, serta memberi amaran terhadap eksploitasi status korporat. HIKAM membingkai keputusan Mahkamah Persekutuan sebagai isu teknikal sempit yang mengancam kedaulatan agama, tanpa sebarang kritikan etika terhadap kandungan fatwa itu sendiri. Ini menunjukkan kesepakatan merentasi spektrum sederhana dan konservatif dalam mempertahankan autoriti fatwa sebagai sesuatu yang suci.
Secara keseluruhan, respons ini memperlihatkan kesepakatan yang ketara merentas institusi dan gerakan. Daripada monarki hingga birokrasi, mufti hingga menteri persekutuan, serta Islamis kanan ekstrem hingga sederhana, pertahanan fatwa menjadi titik temu bersama. Tiada siapa mempersoalkan kandungan etikanya atau kesahihan usaha mendelegitimasi suara feminis. Sebaliknya, reaksi balas ini menegaskan kembali kesucian fatwa sebagai tonggak birokrasi ilahi Malaysia—kebal, terlindung, dan di luar pengawasan demokratik.
Pemenjaraan Epistemik dan Medan Pertarungan Bergender
Pembingkaian SIS sebagai “kultus sesat” mendedahkan bagaimana politik gender berfungsi sebagai medan utama ideologi Islamis. Seperti diperhatikan oleh Haideh Moghissi, Islamisme secara konsisten menggunakan gender untuk menandai sempadan komuniti dan autoriti; pengawalan suara wanita adalah pusat kepada pemeliharaan kemurnian ideologi. Pelabelan SIS sebagai “sesat” bukan isu teologi, tetapi usaha mendisiplinkan suara feminis yang mencabar tafsiran patriarki dalam tradisi intelektual Islam.
Dengan memadamkan sumbangan intelektual SIS, Islamis menafikan wujudnya kepelbagaian ijtihad yang merupakan nadi dan tanah badan tradisi intelektual Islam dan suara SIS dalam menyumbang kepada ranah ijtihad ini. Namun, sebagaimana dihujahkan Ziba Mir-Hosseini, feminisme Islam muncul tepat sebagai penentangan dan benteng terhadap Islamisme dan fundamentalisme agama. Melalui kerja perundangan dan interpretatif mereka, kumpulan seperti SIS mengemukakan visi Islam yang berteraskan keadilan, kesaksamaan, dan ihsan. Penglibatan mereka dalam kerja advokasi dan produksi ilmu pengetahuan berteraskan maqasid al-shariah mencerminkan pemeliharaan agama bukan melalui penutupan epistemik autoritarian, tetapi melalui pembaharuan etika.
Maznah Mohamad pula menunjukkan bagaimana bentuk autoriti agama yang terinstitusikan ini beroperasi secara bergender. Sistem beredar fatwa, mahkamah syariah, dan jabatan agama tidak bersifat neutral; ia secara tidak seimbang menyasarkan hak wanita dalam undang-undang keluarga, kawalan moral, dan penyertaan awam. Serangan terhadap SIS memperlihatkan bagaimana birokrasi ilahi menggerakkan autoritinya untuk mengawal ruang bergender, membungkam tafsiran feminis sambil melindungi norma patriarki daripada kritikan.
Oleh itu, reaksi balas ini merupakan satu bentuk penutupan epistemik. Daripada berbahas tentang visi Islam yang bersaing, aktor Islamis—daripada birokrat hingga NGO—menghasilkan salah maklumat untuk mendelegitimasikan alternatif. Dalam proses ini, fatwa disakralkan sebagai wadah kebenaran ilahi, walaupun ia bersandar pada penghapusan dan salah tafsir.
Mengundurkan Demokrasi Perlembagaan: Peranan Aktor Perundangan Islamis
Kes fatwa SIS bukan sahaja menunjukkan refleks defensif gerakan Islamis dan birokrat agama, tetapi juga peranan tegas aktor perundangan Islamis dalam mengundurkan tatanan perlembagaan Malaysia daripada prinsip demokratik. Melalui kes mahkamah, campur tangan media, dan mobilisasi awam, peguam Islamis menterjemahkan pertikaian perlembagaan menjadi tontonan moral yang mengukuhkan supremasi agama. Intervensi mereka mencerminkan apa yang dihuraikan Tamir Moustafa dalam Constituting Religion sebagai “mahkamah pendapat umum”: pertikaian undang-undang dibungkus semula untuk konsumsi massa, menghasilkan polarisasi dan memperkuat autoriti institusi agama.
ABIM dan IKRAM menunjukkan bagaimana Islamisme institusional beroperasi melalui bahasa undang-undang dan reformasi. Respons pasca-keputusan mereka tidak mempertahankan pluralisme atau etika fatwa, tetapi menuntut pengiktirafan kuasa fatwa secara eksplisit dalam undang-undang persekutuan, penyelarasan sistem sivil dan syariah, serta peluasan tadbir urus Islam. Walaupun dibalut dengan retorik rahmah atau keharmonian teknokratik, tuntutan ini mendedahkan objektif yang konsisten: menginsulasi autoriti agama daripada akauntabiliti demokratik.
Pengamal undang-undang Islamis seperti Zainul Rijal Abu Bakar (peguam Jawatankuasa Fatwa Selangor dan Pengerusi Pembela) serta Zulfakar Ramlee (IKRAM Legal) mengukuhkan logik peluasan ini. Zainul membingkai keputusan Mahkamah Persekutuan sebagai isu teknikal semata-mata, sambil menegaskan bahawa individu dalam SIS masih terikat secara peribadi dengan fatwa dan harus berhenti bercakap tentang Islam. Dr Zulfakar menggambarkan fatwa sebagai produk institusi yang melalui perbahasan rapi dan diperkenankan Sultan, serta menggunakan kes ini untuk berhujah tentang pengukuhan struktur mahkamah syariah. Pembingkaian ini meletakkan fatwa di luar perbahasan etika sambil menuntut pengukuhan institusi yang lebih mendalam.
Peguam lain, seperti Aidil Khalid dari Persatuan Peguam-Peguam Muslim Malaysia (PPMM), membawa pertempuran terus ke ruang awam. Ceramah dan kempen media sosial mengaitkan keputusan SIS dengan perjuangan lebih luas menentang apa yang disebut “liberalisme Islam”, sekali gus memobilisasi kecurigaan terhadap SIS sebagai sebahagian daripada perang ideologi. Dalam hal ini, peguam Islamis bergerak lancar dari mahkamah ke masjid ke media, meluaskan pertikaian fatwa ke dalam imaginasi sosial.
Moustafa turut menunjukkan bahawa pengkodifikasian syariah dalam undang-undang negara moden mengubah tradisi perundangan Islam yang asalnya plural dan interpretatif menjadi sistem yang kaku, hierarkis, dan terpiawai. Di mana fiqh dahulu berkembang melalui ikhtilaf dan perbahasan tidak berhierarki, negara pascakolonial mengenakan struktur mahkamah berhierarki dan statut yang mencerminkan prosedur undang-undang sivil/komon law. Akta Prosedur Jenayah Syariah dan Prosedur Sivil Syariah banyak meminjam kod mahkamah sivil secara langsung, hanya menyingkirkan elemen yang dianggap “tidak sesuai”. Hasilnya ialah apa yang digelar sebagai undang-undang Anglo-Muslim: secara formal moden dan positivis, tetapi asing bagi fuqaha klasik.
Proses pembakuan ini mencipta gambaran syariah sebagai kod undang-undang tertinggi yang dimonopoli oleh negara dan aktor perundangannya. Peguam Islamis memanfaatkan pengkodifikasian ini untuk menuntut kedaulatan syariah, berhujah bahawa kerana syariah telah dibirokratisasikan, ia kini mesti berfungsi sebagai undang-undang tertinggi. Setiap kes mahkamah kemudian dibingkai sebagai justifikasi untuk memperluas supremasi ini, walaupun keputusan secara teknikalnya mengehadkan skopnya.
Dinamik ini mengesahkan tesis Moustafa: badan kehakiman menjadi bukan lagi tapak penyelesaian, tetapi pentas polarisasi. Kekalahan di mahkamah dibingkai sebagai isu teknikal, manakala khalayak digerakkan untuk menuntut institusi agama yang lebih kuat. Aktor perundangan menampilkan diri sebagai profesional neutral, tetapi hakikatnya menyisipkan logik autoritarian ke dalam amalan perlembagaan. Hasil akhirnya ialah pengunduran demokrasi perlembagaan—satu sistem di mana penyertaan demokratik dan prosedur undang-undang dimanfaatkan bukan untuk melindungi hak, tetapi untuk mengukuhkan supremasi agama.
Kesimpulan: Pengajaran daripada Reaksi Balas Fatwa terhadap SIS
Keputusan Mahkamah Persekutuan tidak menafikan martabat Islam atau menyingkirkan nilai spiritual fatwa. Ia sekadar menjelaskan bahawa batas perlembagaan terpakai ke atas dekri agama. Namun, reaksi yang ditimbulkannya—kekecewaan, kepanikan, salah maklumat, dan seruan penapisan—menunjukkan bagaimana fatwa telah diangkat ke tahap yang tidak boleh dipersoalkan. Merentasi monarki, birokrasi, kerajaan, dan gerakan Islamis, pertahanan autoriti fatwa bersatu dalam satu konsensus: autoriti agama adalah kebal.
Reaksi balas terhadap SIS turut memperlihatkan kesan nyata salah maklumat. Walaupun memenangi keputusan perlembagaan, SIS akhirnya ditekan melalui campur tangan Sultan untuk menggugurkan perkataan “Islam” daripada namanya. Pada Julai 2025, organisasi itu mengumumkan bahawa ia akan beroperasi secara rasmi sebagai SIS Forum (Malaysia). Seperti dijelaskan oleh Pengarah Eksekutif Rozana Isa, keputusan ini dibuat bagi melangkaui perdebatan tanpa penghujung tentang nomenklatur dan menumpukan semula pada isu substantif—tunggakan nafkah, poligami sebelah pihak, dan tafsiran undang-undang yang tidak sensitif gender—yang terus menafikan keadilan kepada wanita Muslim.
Kesan salah maklumat ini melangkaui lingkaran Islamis. Pengulas liberal dan sekular, yang sepatutnya mempertahankan SIS atas dasar hak demokratik dan kebebasan sivil, sebaliknya mengulang kecurigaan Islamis tentang “penyalahgunaan Islam”. Malah, satu komentar mencadangkan “pertembungan SIS vs GISB”, menyamakan platform intelektual feminis dengan organisasi berunsur kultus hanya kerana kedua-duanya merupakan syarikat berdaftar.
Salah tafsir ini menunjukkan betapa mendalamnya kempen salah maklumat telah membentuk medan tafsiran. Daripada mencabar autoriti agama yang autoritarian, suara sekular mengukuhkannya dengan mengabsahkan premis bahawa “Islam” memerlukan perlindungan negara daripada penyalahgunaan organisasi. Perbahasan pun beralih daripada hak dan pluralisme kepada kecurigaan institusi, lalu mengecilkan pertahanan demokrasi menjadi pertahanan autoriti agama itu sendiri.
Akhirnya, SIS terpaksa berundur daripada tuntutan simbolik terhadap Islam, walaupun terus menghayatinya melalui kerja perundangan dan advokasi. Hasil ini memperlihatkan paradoks demokrasi Islamis Malaysia: walaupun golongan progresif memenangi kemenangan kehakiman, pertembungan salah maklumat, birokrasi ilahi, dan Islamisme institusional memastikan autoriti kekal kebal daripada kritikan.
Pengajarannya jelas: apabila demokrasi dikosongkan daripada pluralisme dan etika, ia berubah menjadi pentas untuk mempertahankan autoriti, bukannya ruang untuk deliberasi. Reaksi balas fatwa terhadap SIS bukan sekadar kisah sebuah organisasi, tetapi cermin yang memantulkan asas rapuh eksperimen demokrasi Malaysia di bawah bayang-bayang Islamisasi.